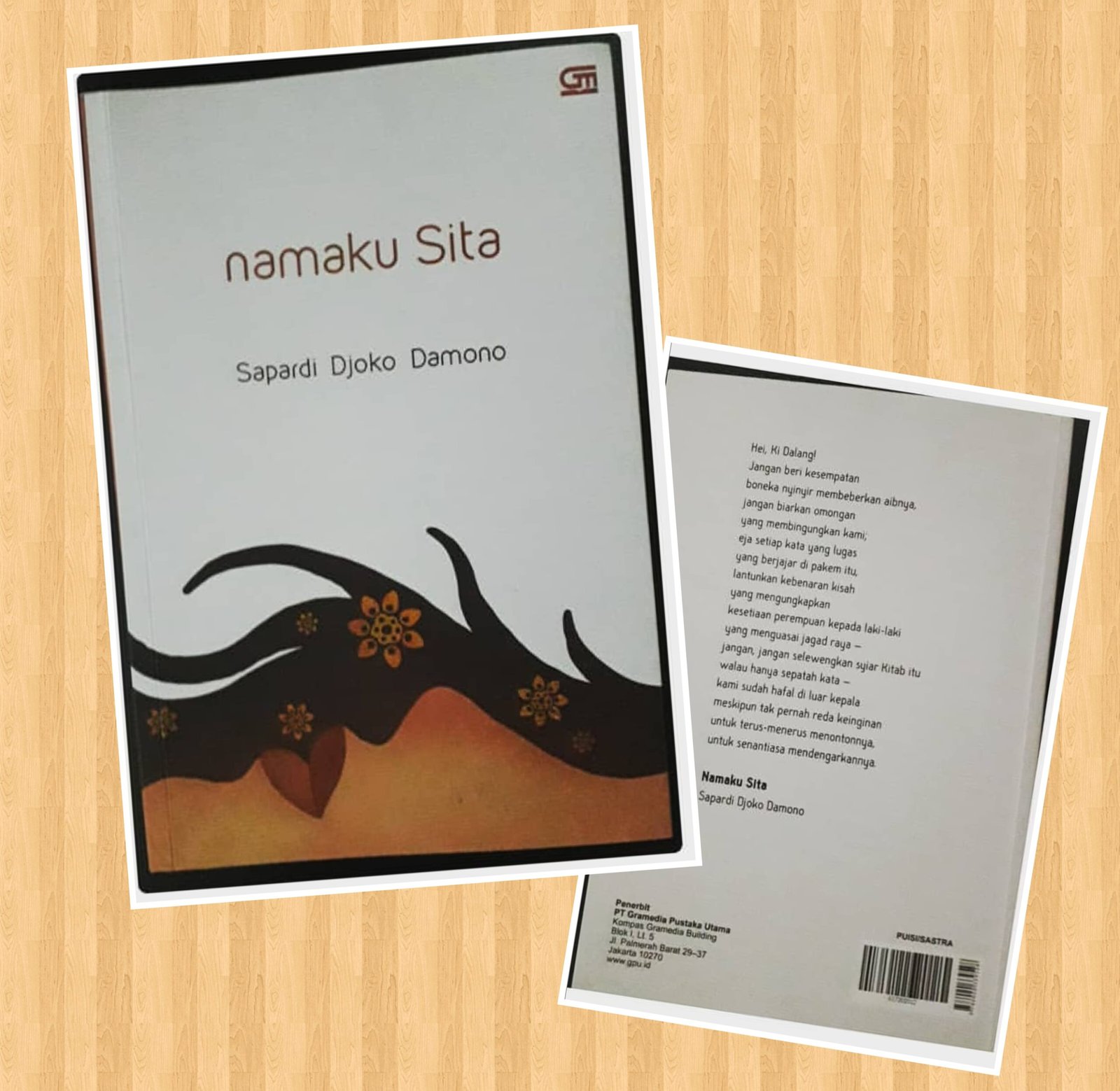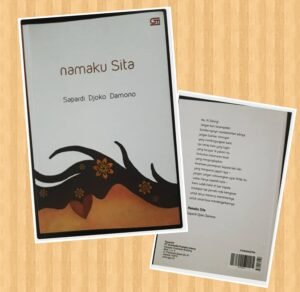“Pilih jurusan yang kamu suka, kamu bebas kok,” kata dosen saya pada
pertemuan perdana kuliah. Ucapannya terdengar membebaskan, hangat, dan
progresif. Saya mengangguk, bukan karena sepakat, tetapi karena saat itu saya
ingin percaya bahwa saya bebas. Namun seiring waktu, saya mulai merasakan
sesuatu yang ganjil: mengapa pilihan yang saya ambil, yang katanya bebas, tetap
terasa diarahkan? Mengapa ‘kebebasan’ itu seperti berjalan di atas rel yang tak
bisa saya belokkan?
Banyak dari kita tumbuh dengan narasi bahwa kita adalah individu
merdeka. Kita bisa memilih jurusan, pekerjaan, bahkan gaya hidup. Namun,
semakin dalam saya menelusuri dunia pendidikan dan kerja, semakin saya
merasa bahwa kebebasan sering kali hanyalah kemasan. Ia lebih mirip opsi-opsi
terbatas yang disusun dalam etalase rapi, kita hanya memilih dalam batasan
yang sudah dipasang sejak awal.
Di Balik Wajah Progresif Modernisasi
Kita hidup di zaman ketika perubahan menjadi mantra. Kita dituntut untuk
adaptif, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika zaman. Kata-kata seperti
reskilling, upskilling, personal branding, dan growth mindset begitu populer,
seolah menjadi indikator utama kelayakan manusia modern.
Namun, adakah kita pernah bertanya siapa yang menyusun standar ini?
Mengapa kita harus terus-menerus ‘meningkatkan diri’ agar relevan? Bukankah
di balik dorongan untuk beradaptasi selalu ada sistem yang menuntut
produktivitas tanpa henti, yang sering kali menjadikan manusia sekadar mesin
kompetisi?
Perubahan memang perlu. Namun jika perubahan itu digerakkan oleh
kepentingan ekonomi-politik tanpa refleksi etik dan keadilan, ia bisa menjelma
alat dominasi baru. Orang-orang yang tak mampu mengikuti perubahan disebut
‘tertinggal’, padahal bisa jadi mereka hanya menolak tunduk pada ritme yang
ditentukan sistem.
Merdeka Belajar yang Tak Merdeka
Contoh paling dekat tampak di dunia pendidikan. Program “Merdeka
Belajar” digadang-gadang sebagai solusi dari kekakuan akademik. Mahasiswa
dikatakan bebas memilih mata kuliah lintas jurusan, magang di luar kampus, dan
menentukan sendiri jalur belajarnya.
Namun, kebebasan itu ternyata tidaklah mutlak. Masih ada batasan
kurikulum nasional, beban SKS minimal, serta ketentuan administratif yang
menyulitkan banyak mahasiswa untuk benar-benar “merdeka”. Sering kali,
mahasiswa dituntut untuk kreatif dalam sistem yang sendiri tidak cukup lentur
untuk memberi ruang pada kreativitas sejati. Alih-alih menjadi subjek merdeka, mahasiswa tetap harus mengikuti arus
institusi yang secara struktural masih menempatkan mereka sebagai objek
kebijakan. Program magang di luar kampus, misalnya, tetap harus terdaftar,
disetujui, dan dinilai oleh institusi. Jadi, sejauh mana mahasiswa benar-benar
menjadi aktor utama dalam pendidikan mereka sendiri?
Kerja Fleksibel yang Membebani
Fenomena serupa terjadi dalam dunia kerja. Narasi kerja fleksibel terutama
setelah pandemi COVID-19, mengangkat wacana kebebasan baru. Kita bisa
bekerja dari rumah, menyesuaikan waktu kerja, bahkan memilih proyek yang
sesuai minat.
Namun di balik itu, jam kerja jadi kabur, notifikasi tak mengenal waktu, dan
ekspektasi perusahaan justru meningkat. Bekerja dari rumah berubah menjadi
bekerja sepanjang waktu. Batas antara ruang privat dan ruang kerja semakin
mengabur.
Fleksibilitas yang dipromosikan bukanlah tentang kebebasan, melainkan
efisiensi untuk perusahaan, bukan untuk pekerja. Dalam praktiknya, banyak
pekerja yang merasa justru lebih kelelahan karena tekanan untuk selalu online,
selalu sigap, dan selalu produktif. Bahkan waktu rehat menjadi bagian dari
strategi manajemen: istirahat supaya bisa kerja lagi lebih giat.
Kebebasan dalam Bingkai Sistem
Dalam kedua dunia ini, pendidikan dan kerja terlihat jelas pola yang sama.
Kita merasa punya pilihan, tapi hanya dalam batas yang telah ditentukan. Kita
merasa punya suara, tapi hanya dalam ruang yang sudah dikondisikan. Kita
merasa bebas, tapi sebenarnya kebebasan itu telah dipagari sejak awal.
Ini bukan kebebasan sejati, tapi kebebasan yang terstruktur atau dalam
istilah sosiolog Pierre Bourdieu, sebuah habitus, struktur sosial yang membentuk
preferensi dan perilaku kita tanpa kita sadari. Kita merasa memilih secara bebas,
padahal kita hanya menjalankan pola-pola yang sudah ditanamkan melalui
sistem pendidikan, ekonomi, dan budaya.
Manusia di Tengah Ilusi Progres
Apa yang terjadi ketika manusia terus dibentuk oleh sistem namun diminta
merasa bebas? Ia menjadi subjek yang bingung. Di satu sisi ia merasa
bertanggung jawab atas pilihannya, namun di sisi lain ia tidak pernah benar-
benar diberi ruang untuk memilih dari awal. Akibatnya, lahirlah kecemasan yang
akut, takut salah arah, takut tak sesuai ekspektasi, takut gagal “mengaktualisasi
diri”.
Di sinilah ironi modernitas bekerja. Ia menjanjikan kebebasan, tapi justru
menciptakan tekanan. Ia menjanjikan kemajuan, tapi sering kali mengorbankan
keseimbangan batin. Ia menjanjikan ruang, tapi menyempitkan waktu dan makna
hidup.
Kesadaran sebagai Tindakan Radikal
Lantas, apakah kita sepenuhnya terjebak? Tidak. Di sinilah pentingnya
kesadaran. Kebebasan sejati bukanlah soal banyaknya pilihan yang tersedia,
tetapi kemampuan untuk melihat struktur di balik pilihan-pilihan itu, lalu
menentukan arah secara sadar dan kritis.
Kesadaran inilah yang bisa menjadi tindakan radikal dalam masyarakat hari
ini. Bukan dalam arti kekerasan atau penolakan total, tapi dalam bentuk refleksi
mendalam, mempertanyakan narasi-narasi besar, mengidentifikasi siapa yang
diuntungkan, dan berani mengambil jalan berbeda jika perlu.
Kebebasan sebagai Proses, Bukan Produk
Pada akhirnya, kebebasan bukanlah suatu kondisi yang selesai, melainkan
proses yang terus-menerus diperjuangkan. Ia lahir dari keberanian untuk
mempertanyakan, bukan hanya menerima. Ia tumbuh dari refleksi yang jujur
atas dunia dan diri kita sendiri.
Kita boleh saja hidup dalam sistem, tapi bukan berarti kita harus menjadi
budaknya. Selama kita terus bertanya, berpikir, dan memilih dengan kesadaran,
kita masih punya harapan. Karena kebebasan sejati bukanlah soal keluar dari
sistem, tetapi hidup di dalamnya dengan mata terbuka dan hati yang tak mudah
dibeli.