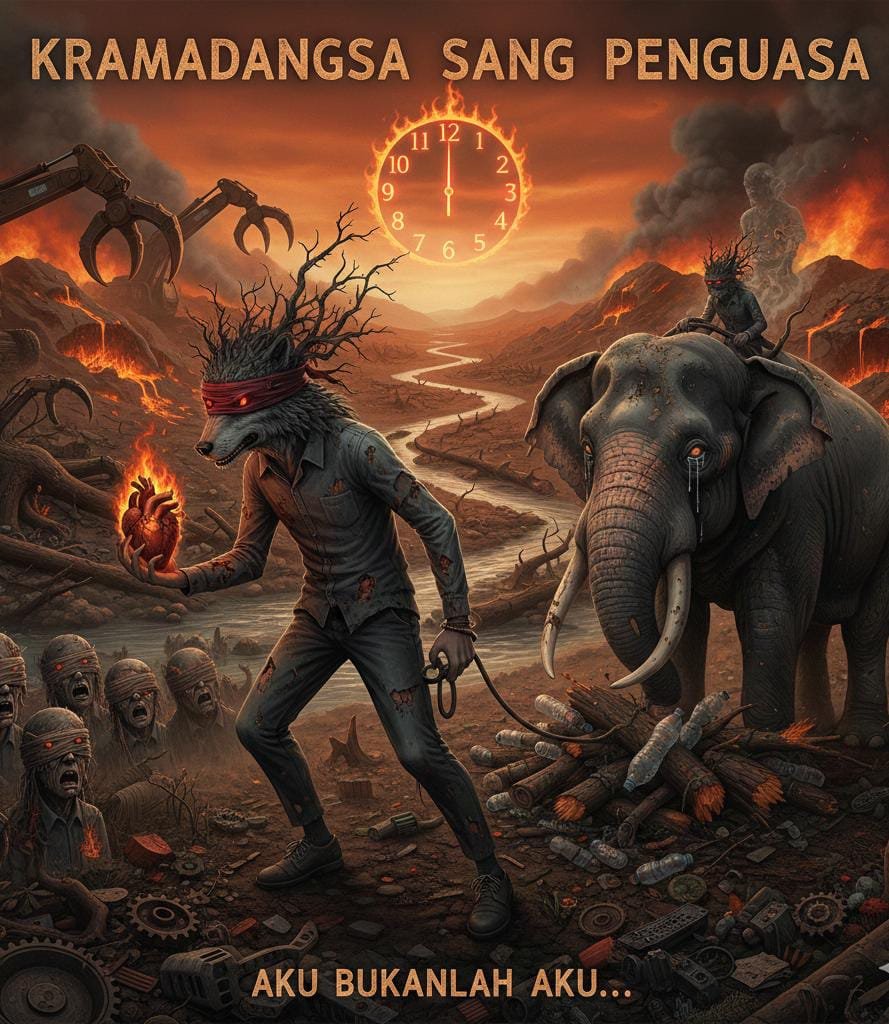Dalam kehidupan manusia, bahasa berfungsi lebih dari sekadar komunikasi; ia juga merupakan cara utama dalam membentuk pola pikir. Walter J. Ong, seorang intelektual yang menekankan hubungan antara kelisanan dan keaksaraan, memandang bahasa—baik yang diucapkan maupun yang tertulis—sebagai teknologi mental yang membangun kesadaran manusia. Pemikirannya menjadi penting ketika kita memperhatikan dinamika komunikasi masa kini yang ditandai oleh persaingan halus antara suara dan tulisan dalam memperebutkan makna. Di tengah transformasi media dan budaya, suara dan tulisan tidak hanya ada berdampingan, tetapi juga saling berkompetisi, saling memengaruhi, bahkan saling meniru.
Sejak awal, kelisanan telah menjadi cara utama dalam interaksi manusia. Melalui suara, orang dapat membangun kedekatan, menciptakan makna dengan spontan, dan melestarikan tradisi. Ong menyebut kelisanan sebagai jenis komunikasi yang bergantung pada konteks, hubungan langsung, dan ingatan bersama. Dalam tradisi lisan, makna hadir sesuai dengan situasi: nada, intonasi, gerakan, dan emosi yang ditunjukkan saat berbicara. Suara berfungsi sebagai wadah bagi identitas budaya serta ruang refleksi yang bersifat kolektif. Banyak masyarakat tradisional menyampaikan cerita rakyat, nasihat, dan hukum adat secara lisan yang diwariskan melalui ingatan, dilengkapi oleh rumus, pengulangan, dan irama.
Namun, kehadiran tulisan mengubah seluruh situasi. Ong menyebut perubahan ini sebagai peralihan kesadaran: dari kesadaran lisan ke kesadaran tulis. Dengan tulisan, manusia dapat memindahkan ide dari konteks kejadian ke dalam teks. Apa yang sebelumnya mengalir dalam konteks lisan sekarang dibekukan dalam huruf dan simbol. Dengan tulisan, individu dapat merenungkan kembali, menyusun ulang, bahkan mempertanyakan hal-hal yang sebelumnya diterima tanpa ragu dalam tradisi lisan. Tulisan memperkenalkan jarak: antara penulis dan pembaca, antara ide dan tindakan, serta antara masa lalu dan masa kini. Namun, jarak ini justru menciptakan ketelitian, analisis, dan refleksi.
Dari perspektif Ong, tulisan lebih dari sekadar alat perekaman. Ia adalah teknologi yang mengubah cara berpikir. Ketika manusia mulai menulis, mereka menyusun ide secara garis besar, membangun argumen dengan sistematis, dan menciptakan konsep abstrak yang sulit berkembang dalam budaya lisan. Itulah sebabnya ilmu pengetahuan, filsafat, dan hukum modern muncul dalam budaya tulis. Tulisan memberikan ruang bagi kestabilan makna: apa yang ditulis dapat dievaluasi, dikritik, dan dipertahankan tanpa mengandalkan keberadaan penutur.
Namun, modernitas membawa fenomena baru berupa media digital. Dunia digital menghasilkan apa yang Ong sebut sebagai “kelisanan sekunder”—sebuah bentuk kelisanan yang muncul dari teknologi tulisan. Di media sosial, pesan ditransmisikan melalui teks, tetapi gaya yang digunakan sering kali menyerupai percakapan lisan. Ungkapan seperti “haha,” emoji, penggunaan huruf kapital untuk penekanan, atau tulisan tanpa tanda baca meniru spontanitas dari suara. Di sisi lain, ujaran sekarang mengikuti pola yang lebih sesuai dengan tulisan: singkat, jelas, dan tersegmentasi. Telepon pintar membuat orang berbicara dengan cara menulis dan menulis dengan cara berbicara. Suara dan tulisan kini tidak lagi dipisahkan oleh fungsi yang jelas; keduanya beririsan.
Perlombaan antara makna suara dan tulisan semakin jelas saat kita mengamati cara berkomunikasi masyarakat modern. Di satu sisi, suara kembali menjadi penting melalui podcast, pesan suara, dan video pendek. Manusia seolah menemukan kembali kedekatan dalam komunikasi lisan. Suara menciptakan kedekatan yang tidak bisa diberikan oleh tulisan. Intonasi dapat menyampaikan perasaan keraguan, marah, atau semangat yang sulit diekspresikan dalam bentuk tulisan. Dalam banyak situasi, suara memungkinkan pemahaman yang lebih cepat: seseorang bisa menjelaskan sesuatu dalam 30 detik berbicara dibandingkan 3 paragraf tulisan.
Di sisi lain, tulisan masih menjadi sarana yang penting untuk mendokumentasikan dan merenung. Walaupun kita hidup dalam era digital yang cepat, tulisan tetap merupakan cara utama untuk berpikir lebih dalam. Artikel, esai, dokumen, dan buku menunjukkan bahwa kemampuan menulis tidak tergantikan oleh lisan digital. Tulisan juga memungkinkan penyebaran informasi secara luas sambil menjaga struktur dan kesinambungan. Dalam hal ini, pertempuran makna bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang siapa yang lebih cocok dengan konteks komunikasi tertentu.
Pertikaian ini memiliki dampak budaya. Ketika suara menjadi mayoritas, masyarakat cenderung lebih reaktif, emosional, dan situasional. Informasi dipahami melalui kesan, bukan analisis. Sebaliknya, tulisan yang dominan mengarah pada analisis, rinci, dan pengambilan jarak. Dalam banyak diskursus, terjadi benturan antara mereka yang mengedepankan kedalaman (melalui tulisan yang panjang) dengan mereka yang lebih mengutamakan kecepatan (melalui ucapan yang cepat dan singkat). Media sosial semakin memperburuk ketegangan ini dengan menyediakan platform yang mendukung komunikasi cepat, instan, dan berbasis kesan.
Namun, tidak tepat untuk menyebut salah satu lebih baik dari yang lain. Ong mengingatkan bahwa keduanya bukan kompetitor yang saling menyingkirkan, melainkan dua bentuk kesadaran yang saling melengkapi. Suara membantu orang merasakan, sedangkan tulisan mendukung proses berpikir. Suara mengikat manusia secara sosial, di sisi lain tulisan memberikan kebebasan untuk berpikir jauh melampaui konteks. Dalam era modern, keduanya membangun ekosistem komunikasi yang saling terkait.
Jika kita perhatikan perkembangan budaya saat ini, suara dan tulisan tidak hanya bersaing untuk mendapatkan makna, tetapi juga menciptakan arti dengan cara baru. Ketika seseorang mengirim pesan suara diikuti dengan teks yang panjang, ia sebenarnya menggabungkan dua teknologi kesadaran. Di ruang publik, pidato yang viral biasanya dibagikan dalam bentuk kutipan tertulis. Sebaliknya, tulisan pendapat seringkali diperkuat dengan video atau rekaman suara sebagai bukti emosional. Perpaduan ini menegaskan bahwa budaya modern tidak perlu memilih salah satu; kita hidup dalam dunia di mana suara dan tulisan saling melengkapi dalam pola yang selalu berubah.
Pada akhir hari, konflik antara suara dan tulisan tidak tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana manusia memahami realitas. Seiring teknologi terus berkembang, suara dan tulisan akan terus bernegosiasi untuk menemukan tempatnya dalam kehidupan kita. Walter J. Ong mengajarkan bahwa setiap perubahan dalam media komunikasi membawa perubahan dalam pola pikir. Ketika suara dan tulisan bersaing untuk mendapatkan makna, kita menyaksikan evolusi cara manusia membangun pengetahuan, memahami diri, dan membentuk dunia.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin tidak menyadari ketegangan ini. Namun, setiap kali kita memutuskan untuk menelepon atau mengirim pesan teks, membuat catatan atau merekam audio, membaca artikel atau menonton video, sebenarnya kita sedang memilih media mana yang lebih kita percayai untuk menafsirkan sesuatu. Pertanyaan terakhir adalah: apakah kita lebih suka memahami dunia melalui kedekatan suara atau melalui urutan tulisan? Mungkin jawabannya bukan terletak pada memilih salah satu, melainkan menggunakan keduanya untuk menciptakan pemahaman yang lebih utuh. Suara dan tulisan akan terus bersaing untuk mendapatkan makna, dan dari persaingan inilah, kesadaran manusia terus berkembang.
Namun demikian, istilah “tanpa tulisan” masih merupakan penilaian negatif, menyiratkan bias tulis. Ulasan yang ada saat ini menyarankan penggunaan istilah yang lebih positif dan tidak menyakitkan, yaitu “lisan”. Pernyataan Levi-Strauss yang banyak di kutip (1966: 245) “the savage mind totalizes” (pikiran liar senang menggabung-gabungkan) akan diganti menjadi “the oral mind totalitez”.