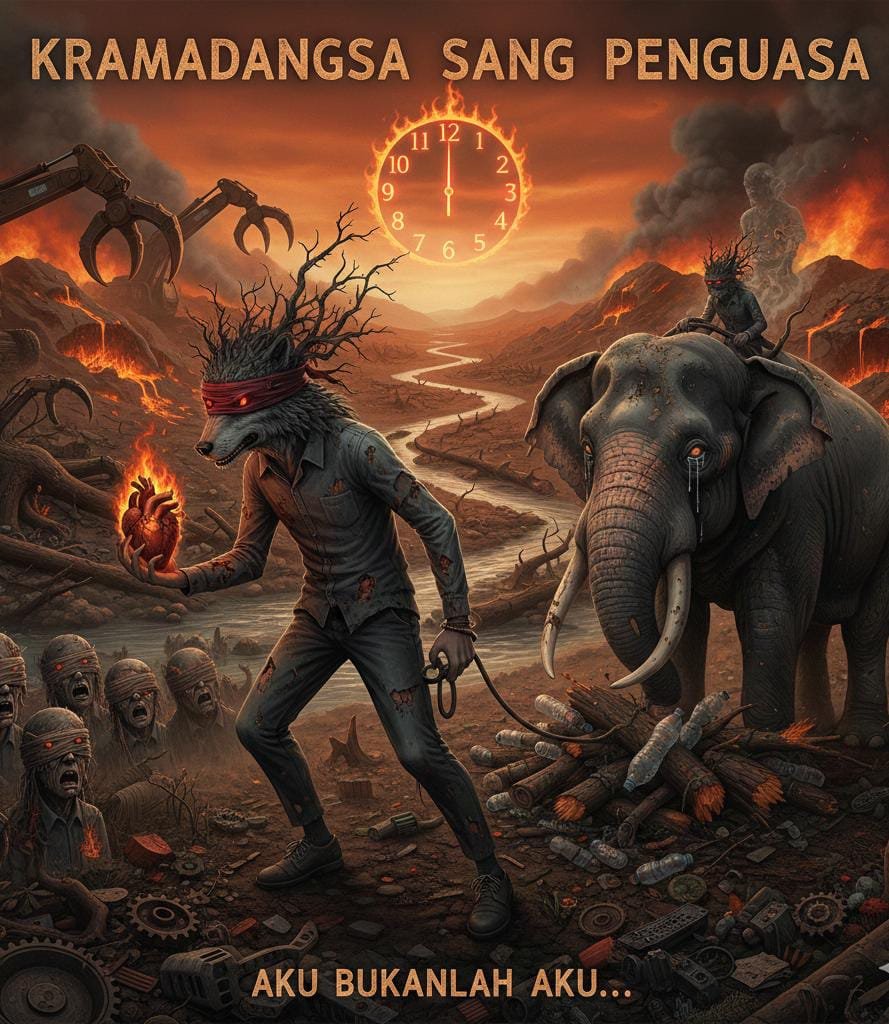Oleh: Luthfi Azizan
Di sebuah senja yang kian pekat, ketika langit Jakarta atau entah kota mana pun merayap perlahan ditelan temaram, kita seringkali menemukan diri kita sendiri. Terjebak dalam riuhnya suara notifikasi ponsel, di antara deru mesin-mesin yang tak pernah lelah bekerja, atau dalam keheningan yang justru terasa ramai dengan pikiran sendiri. Dunia, seolah-olah, telah belajar cara tercepat untuk berputar, namun lupa cara paling sederhana untuk merasa.
Kita hidup di zaman di mana informasi mengalir seperti air bah, namun kasih sayang terasa semakin mengering. Kisah-kisah pilu melintas di layar gawai kita, hanya untuk lenyap ditelan berita viral berikutnya. Ada kecelakaan di jalan, ada jerit lapar dari negeri seberang, ada tangis pilu di sudut kota, namun seringkali yang tersisa hanyalah dengungan kosong di telinga kita. Hati, seolah-olah, telah ditumbuhi lumut tebal, membuat kita sulit merasakan getar kepedihan orang lain.
Mengapa empati, si permata paling berharga dalam dada manusia, kian pudar? Mengapa kepekaan diri, kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasa, seolah menjadi barang langka? Apakah kita terlalu sibuk berlomba, hingga lupa menengok ke samping? Apakah kita terlalu asyik membangun menara ego, hingga pondasi kemanusiaan kita retak?
Ini merupakan undangan untuk menepi sejenak dari hiruk-pikuk, untuk menatap lebih dalam ke jendela hati kita sendiri. Kita akan menelusuri jejak-jejak kearifan yang ditinggalkan oleh para pemikir besar, dari seorang filsuf di Konigsberg yang mencoba memahami moralitas universal, seorang pendidik di Jawa yang memanusiakan muridnya, hingga seorang ulama dari Baghdad yang menyerukan penyucian jiwa. Mereka, dengan cara mereka sendiri, telah mengajarkan kita bahwa empati bukanlah sekadar perasaan, melainkan sebuah cahaya yang harus dirajut, sehelai demi sehelai, agar dunia yang kian membeku ini kembali hangat.
Bisikan dari Königsberg: Kant dan Etika Kewajiban yang Menggugah
Jauh di sebuah kota kecil bernama Königsberg, Prusia Timur, pada abad ke-18, hiduplah seorang filsuf dengan pikiran setajam pisau bedah dan jiwa sehangat lilin yang tak pernah padam. Namanya Immanuel Kant. Ia adalah sosok yang mungkin terlihat kaku dengan rutinitasnya, namun pikirannya mampu menembus batas-batas kemanusiaan yang paling mendasar.
Kant tak banyak bicara tentang “perasaan” dalam etika. Baginya, moralitas sejati bukanlah soal seberapa besar kita merasa kasihan, atau seberapa banyak kebahagiaan yang dihasilkan dari tindakan kita. Bukan. Moralitas, kata Kant, adalah soal kewajiban. Sebuah kewajiban yang muncul dari akal budi murni, yang universal dan tak tergoyahkan oleh emosi sesaat.
Di sinilah letak bisikan pertama menuju empati yang hakiki. Kant memperkenalkan konsep “imperatif kategoris”. Sebuah perintah moral yang berlaku mutlak, tanpa syarat. Salah satu rumusan terkenalnya adalah: “Bertindaklah hanya berdasarkan maksim (prinsip) yang kamu kehendaki agar dapat menjadi hukum universal.”
Apa artinya ini bagi empati? Ini berarti, sebelum kita bertindak atau berkata-kata kepada orang lain, kita harus bertanya pada diri sendiri: “Apakah saya ingin semua orang di dunia ini bertindak seperti ini? Apakah saya ingin jika saya berada di posisi orang lain, saya diperlakukan seperti ini?” Jika kita tidak ingin diperlakukan kasar, maka jangan berlaku kasar. Jika kita tidak ingin diabaikan, maka jangan mengabaikan.
Bagi Kant, empati bukanlah soal “merasa kasihan” sebagai motivasi utama. Itu adalah sebuah konsekuensi logis dari sebuah kesadaran moral yang mendalam: bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama, dan kita memiliki kewajiban universal untuk menghormati martabat itu. Empati, dalam kacamata Kant, adalah sebuah keharusan akal budi untuk mengakui kemanusiaan dalam diri orang lain, bukan sekadar respons emosional semata. Ini adalah fondasi pertama untuk merajut kepekaan: sebuah komitmen moral yang tak bisa ditawar.
Tangan Memerdekakan dari Tanah Jawa: Ki Hajar Dewantara dan Pendidikan Humanisme
Dari bumi Königsberg yang dingin, kita kini melabuhkan hati ke tanah Jawa yang hangat, di awal abad ke-20. Di sana, seorang bangsawan berjiwa merdeka, Raden Mas Soewardi Soerjaningrat—yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara—sedang merajut mimpi besar tentang sebuah pendidikan yang membebaskan, sebuah pendidikan yang bukan hanya mengisi kepala, melainkan juga menumbuhkan hati.
Ki Hajar Dewantara, dengan segala kearifan lokalnya, menyadari bahwa pendidikan bukanlah sekadar deretan angka dan teori. Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia, mengembalikan setiap individu pada fitrahnya sebagai makhluk yang berbudaya, berakal, dan yang paling penting, memiliki rasa. Ia percaya bahwa di dalam diri setiap anak, ada benih-benih kebaikan yang harus disirami agar tumbuh menjadi pohon yang rindang, tempat banyak kehidupan bisa bernaung.
Filosofi legendarisnya, “Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani”, adalah tiga bait puisi yang seharusnya tertanam di setiap sanubari. Di depan, seorang guru harus memberi teladan (Ing Ngarsa Sung Tuladha) – bukan hanya dalam ilmu, melainkan dalam sikap, dalam kepekaan terhadap sesama. Di tengah, guru harus membangun semangat dan menciptakan peluang (Ing Madya Mangun Karsa) – mendorong siswa untuk berkreasi, berdiskusi, dan memahami dunia di sekitar mereka. Dan di belakang, guru harus memberi dorongan dan arahan (Tut Wuri Handayani) – menumbuhkan kemandirian dan keberanian untuk menghadapi hidup.
Dalam bingkai filosofi ini, empati bukanlah mata pelajaran terpisah. Empati adalah denyut nadi pendidikan itu sendiri. Bagaimana seorang anak bisa berempati jika ia tidak pernah melihat teladan empati dari gurunya? Bagaimana ia bisa merasakan penderitaan orang lain jika pendidikan hanya sibuk mengisi otaknya dengan rumus dan hapalan, tanpa pernah menyentuh hatinya dengan cerita-cerita tentang kehidupan?
Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita bahwa empati adalah hasil dari sebuah pendidikan yang menyeluruh, yang tidak hanya mengasah kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual. Ini adalah proses panjang, sebuah upaya kolektif untuk membentuk manusia yang memiliki kepekaan terhadap lingkungan, sesama, dan dirinya sendiri. Dari tangan memerdekakan Ki Hajar Dewantara, kita belajar bahwa merajut kepekaan diri adalah bagian tak terpisahkan dari merajut peradaban.
Cahaya dari Baghdad: Imam Al-Ghazali dan Penyucian Jiwa
Kini, mari kita merentangkan sayap ke masa lalu yang lebih jauh, ke abad ke-11 di kota Baghdad yang megah, tempat ilmu pengetahuan dan spiritualitas bersemi. Di sana, seorang ulama besar, pemikir agung yang dijuluki Hujjatul Islam—Imam Al-Ghazali—menyuarakan sebuah kebenaran universal yang melampaui batas agama dan waktu: pentingnya penyucian jiwa.
Dalam karyanya yang monumental, Ihya’ Ulumuddin (Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama), Al-Ghazali tak henti-hentinya menekankan bahwa ilmu tanpa amal adalah sia-sia, dan amal tanpa hati yang bersih adalah hampa. Baginya, jalan menuju kebahagiaan sejati, menuju kedekatan dengan Tuhan, adalah melalui pembersihan hati dari segala penyakit dan pengisiannya dengan akhlak mulia.
Apa hubungan ini dengan empati? Al-Ghazali mengajarkan bahwa hati manusia adalah cermin. Jika cermin itu kotor, berkarat, atau tertutup debu kesombongan, iri hati, kebencian, atau egoisme, maka ia tak akan mampu memantulkan cahaya kebaikan, apalagi menangkap bayangan penderitaan orang lain. Hati yang gelap oleh dosa dan sifat tercela, adalah hati yang buta terhadap luka sesama.
Proses tazkiyatun nafs—penyucian jiwa—adalah sebuah perjuangan spiritual untuk membersihkan hati dari sifat-sifat buruk (seperti ghibah, hasad, riya’) dan menggantinya dengan sifat-sifat terpuji (seperti syukur, sabar, tawakal, dan yang terpenting, rahmat atau belas kasih). Ketika hati bersih, ia akan menjadi peka. Ia akan merasakan sakitnya orang lain seolah itu adalah sakitnya sendiri. Ia akan merasakan kebahagiaan orang lain seolah itu adalah kebahagiaannya.
Al-Ghazali mengajarkan kita bahwa empati bukanlah sekadar tuntutan moral atau hasil pendidikan. Empati adalah pancaran dari jiwa yang suci, buah dari kesadaran spiritual bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan ciptaan. Dari cahaya Baghdad, kita belajar bahwa merajut kepekaan diri adalah sebuah perjalanan spiritual untuk kembali pada fitrah kemanusiaan yang paling mulia.
Baca Juga: Imam Ghazali: Sang Hujjatun Islam
Merajut Benang-Benang Cahaya: Sintesis Antara Nalar, Hati, dan Spiritualitas
Kini, setelah menyusuri jejak-jejak kearifan dari Königsberg, Tanah Jawa, dan Baghdad, tibalah saatnya kita merajut benang-benang cahaya ini menjadi sehelai kain kepekaan yang utuh.
Dari Immanuel Kant, kita belajar bahwa empati bukanlah sekadar perasaan instan, melainkan fondasi nalar moral—sebuah kewajiban universal untuk menghormati martabat setiap insan, memperlakukan mereka sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ini adalah jembatan akal budi yang memaksa kita keluar dari sangkar egoisme.
Dari Ki Hajar Dewantara, kita memahami bahwa empati adalah buah dari pendidikan yang memanusiakan, sebuah proses panjang yang menuntun tangan kita untuk memberi teladan, membangun semangat, dan mendorong kemandirian. Ini adalah cara praktis untuk menumbuhkan rasa peduli melalui interaksi dan keteladanan.
Dan dari Imam Al-Ghazali, kita menyadari bahwa empati adalah pancaran dari jiwa yang tersucikan, hasil dari perjuangan spiritual membersihkan hati dari karat-karat egoisme dan menggantinya dengan rahmat dan belas kasih ilahiah. Ini adalah akar terdalam yang memberi kekuatan pada cabang-cabang kebaikan.
Merajut kepekaan diri bukanlah tugas yang ringan. Ia membutuhkan nalar untuk memahami kewajiban kita, pendidikan untuk membentuk karakter kita, dan spiritualitas untuk menyucikan hati kita. Ini adalah sebuah sintesis yang sempurna: akal menuntun, pendidikan membentuk, dan hati yang bersih menjadi sumber mata airnya. Ketika ketiga elemen ini bersatu, empati tidak lagi menjadi sebuah konsep abstrak, melainkan sebuah kekuatan nyata yang mampu menggerakkan kita untuk bertindak.
Baca Juga: Balada Sebuah Tumbler
Di ujung perjalanan ini, ketika senja kembali menyapa jendela hati, kita menyadari bahwa dunia yang kian membeku bukanlah takdir yang tak bisa diubah. Dinginnya sikap acuh tak acuh, tebalnya dinding ketidakpedulian, dan derasnya arus egoisme, semuanya bisa dicairkan oleh satu hal: cahaya empati.
Empati adalah pilihan. Pilihan untuk tidak menutup mata saat melihat luka. Pilihan untuk tidak menutup telinga saat mendengar tangisan. Pilihan untuk tidak mengunci hati saat ada kesempatan untuk memberi. Ini adalah keberanian untuk melampaui diri sendiri, untuk merasakan getaran jiwa orang lain, dan untuk bertindak berdasarkan pemahaman itu.
Mari kita, para penjelajah rasa di zaman yang serba cepat ini, mulai merajut benang-benang cahaya itu. Dari setiap kewajiban moral yang kita penuhi, dari setiap tindakan kecil yang memanusiakan, dan dari setiap upaya membersihkan hati dari karat-karat dunia. Mungkin hanya sehelai demi sehelai, setitik demi setitik, namun rajutan kecil itu lambat laun akan membentuk sehelai kain kehangatan yang cukup besar untuk menyelimuti dunia.
Sebab pada akhirnya, di bawah langit yang sama, kita semua adalah musafir yang saling bertemu. Dan di antara semua bekal yang kita bawa, empati adalah lentera paling terang yang akan menuntun kita pulang, menuju sebuah dunia yang tak lagi membeku, melainkan hangat oleh sentuhan kemanusiaan.