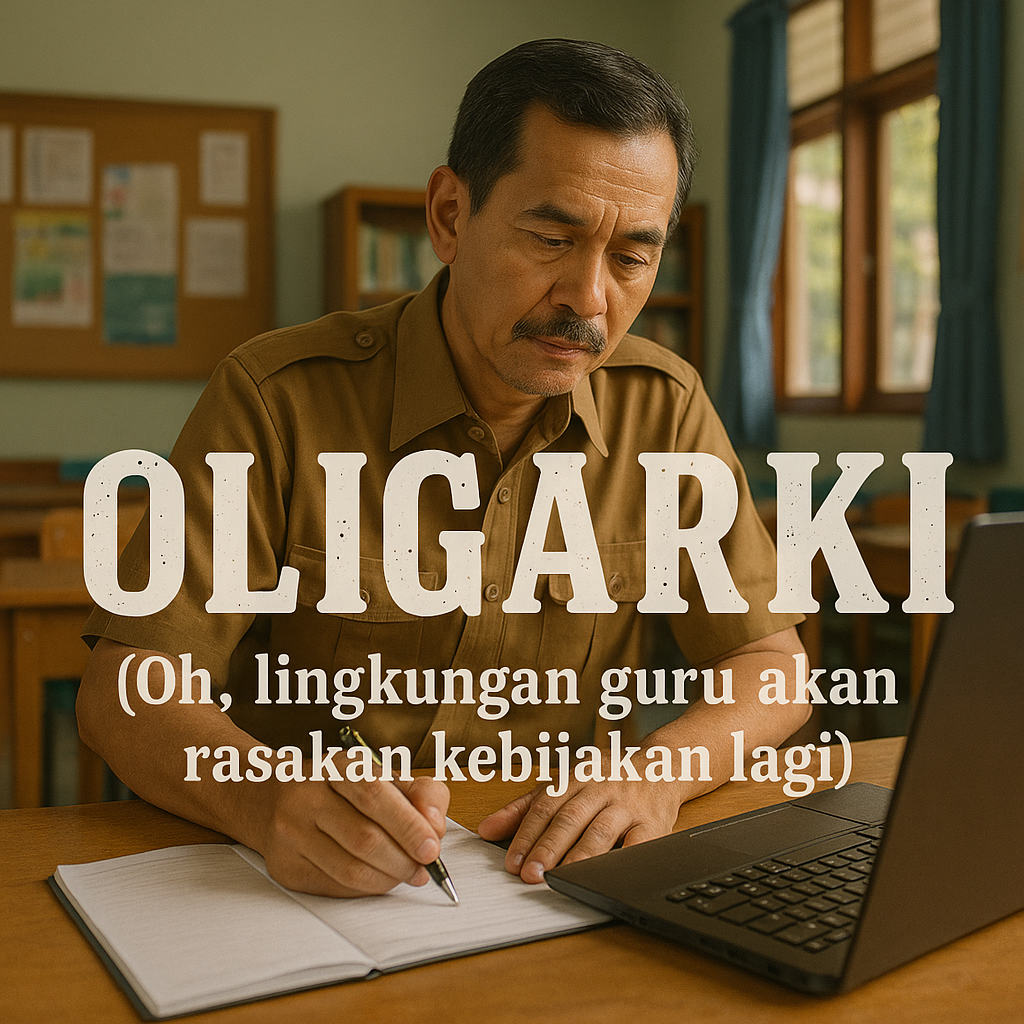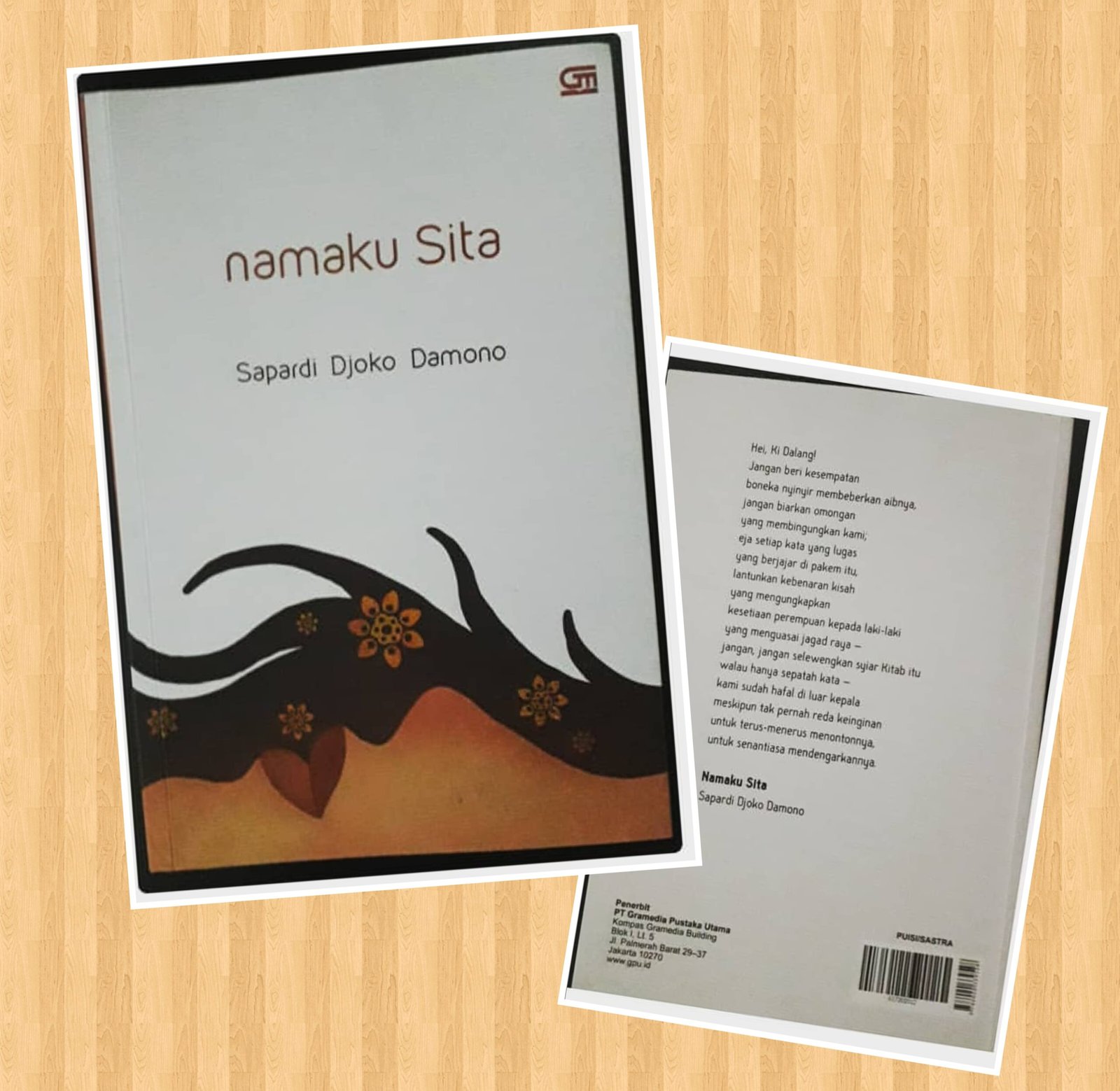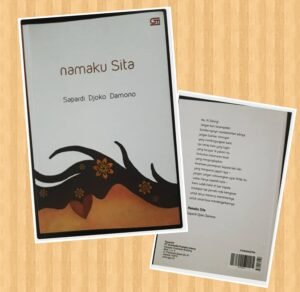“Kesalahan seorang pemimpin adalah akibat dari salahnya pendidikan, khususnya seorang guru,” ucap Fauzi tiba-tiba saat suasana sekolah masih lengang dan dingin pagi itu.
Aku tersentak mendengar ucapannya. Nada suaranya begitu mantap dan berani, seakan menantang siapa pun yang mendengarnya untuk berpikir lebih dalam. Aku baru saja bersiap-siap untuk mengikuti upacara bendera, tetapi perkataan Fauzi langsung mendobrak pikiranku yang masih setengah sadar.
Aku menoleh ke arahnya, mencoba memastikan apakah dia benar-benar serius dengan ucapannya barusan. Melihat raut wajahnya yang dingin dan penuh keyakinan, aku tahu ini bukan sekadar omongan biasa.
“Kau serius, Zi? Maksudmu apa? Kenapa guru yang disalahkan?” tanyaku dengan nada heran.
Fauzi mendesah pelan, seolah-olah sudah menduga aku akan bertanya hal itu.
“Ya, aku serius. Coba pikirkan, siapa yang mendidik generasi yang nantinya akan jadi pemimpin? Guru, kan? Kalau para pemimpin kita membuat kebijakan yang salah, apa itu bukan berarti ada yang salah juga dengan pendidikan mereka sejak awal?”
Aku terdiam sejenak. Aku tak sepenuhnya setuju, tapi juga tak bisa sepenuhnya menolak argumennya.
“Tapi, … bukankah pendidikan juga dipengaruhi oleh sistem? Bagaimana kalau sistem pendidikannya yang sudah rusak sejak dulu?” balasku mencoba mencari celah dalam logikanya.
“Itulah poinku. Sistem pendidikan kita terus dikelola oleh pemimpin-pemimpin yang lahir dari sistem yang sama. Seolah-olah lingkaran ini tidak pernah berakhir. Kau tahu siapa yang akhirnya jadi korban?”
Aku mengerutkan kening, lalu mencoba menebak, “Mungkin, guru-guru seperti kita?”
“Ya, tepat sekali. Kita. Apalagi aku, seorang guru PPPK. Aku sadar betul posisiku tidak setara dengan guru-guru PNS meskipun tugas dan tanggung jawab kita sama. Bahkan lebih berat karena kita harus berjuang dengan segala keterbatasan,” jawab Fauzi tegas.
Aku bisa merasakan ada luapan emosi dalam kata-katanya. Fauzi memang dikenal sebagai sosok guru yang kritis. Ia tak pernah segan mengutarakan pendapatnya, terutama jika menyangkut isu-isu keadilan.
“Jadi, maksudmu kesalahan regulasi kesejahteraan PPPK ini juga karena kesalahan dari guru sendiri dalam menentukan pemimpinnya?” tanyaku mencoba menafsirkan lebih jauh maksudnya.
“Begitulah. Praktik seperti ini sudah ada sejak lama. Sama seperti praktik-praktik lain yang tetap dilanggengkan turun-temurun demi memuaskan kepentingan sebagian kecil orang. Sementara itu, kita hanya bisa diam menerima.”
Aku ingin membalasnya lagi, tetapi entah kenapa aku merasa pikiranku tak setajam miliknya. Lagi pula, sekolah sudah mulai ramai. Suara riuh para siswa yang datang membuat kami sadar bahwa waktu upacara semakin dekat. Aku menoleh ke arah lapangan, melihat para siswa mulai berbaris rapi di bawah tiang bendera.
“Kita lanjutkan nanti saja, Zi. Upacara sudah mau dimulai,” ujarku mencoba mengakhiri pembicaraan yang semakin membuat pikiranku penuh.
“Baiklah. Tapi jangan lupa, pikirkan baik-baik apa yang kubilang tadi. Kadang, perubahan dimulai dari mereka yang mau mempertanyakan.”
Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Kata-katanya terus terngiang di pikiranku sepanjang upacara bendera. Di tengah lautan siswa dan suara pembacaan teks Pancasila, aku masih bergulat dengan pikiranku. Benarkah kita ini korban? Atau sebenarnya bagian dari masalah itu sendiri?
Aku kembali mengingat peranku sebagai guru PPPK. Aku sadar betul posisiku tak setara dengan para guru berstatus PNS. Bukan hanya soal status, tapi juga soal tunjangan dan fasilitas yang diterima. Tunjangan daerah yang kudapatkan setiap bulan tak sebanding, bahkan ada yang selisihnya hingga tiga kali lipat lebih besar. Aku pernah mendengar bisik-bisik di ruang guru, tentang bagaimana seorang guru PNS baru saja membeli kendaraan baru dari hasil tabungannya. Aku hanya bisa memimpikannya. Kehadiran Fauzi yang tetap membuatku semangat sejauh ini.
Aku sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Fauzi. Baginya, menikmati senyum para siswa ketika mereka berhasil menyelesaikan sebuah karya adalah sebuah kepuasan batin yang tak tergantikan. Ketika satu demi satu tulisan muridnya terbit dalam bentuk buku, ada perasaan bangga yang mengalir dalam dirinya. Aku tahu betapa sulitnya menumbuhkan kecintaan terhadap menulis di kalangan remaja. Namun, kesulitan itu seolah lenyap setiap kali ia melihat hasil karya siswanya terpajang di perpustakaan sekolah. Di sisi lain, ada satu hal yang terus mengganjal hatinya. Ia merasa kesulitan mengajak sesama guru untuk menulis.
“Oh, lihatlah! Guru berkarya kesampingkan diri. Oligarki,” bisikku dalam hati.
Di tengah kesenjangan yang mengimpit kami, Fauzi tetap bekerja sepenuh hati. Ia tahu bahwa mengeluh hanya akan memperburuk suasana hati. Maka, ia memilih untuk bertahan, menyalakan semangatnya sendiri, dan terus berkarya.
“Aku hanya berharap. Oh, lindungilah guru agar keadilannya terpenuhi. Oligarki,” bisikku lagi meresapi kegelisahan.
Setiap hari, Fauzi datang lebih awal ke sekolah. Ruang kelas yang masih kosong adalah tempat favoritnya. Di sana, ia duduk, membuka laptop, dan mulai menulis. Bagi sebagian orang, menulis mungkin sekadar aktivitas biasa. Namun baginya, menulis adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang ia rasakan. Dengan menulis, ia ingin menunjukkan bahwa seorang guru tak perlu bergantung pada status untuk bisa berkarya.
Upacara pun selesai. Aku kembali ke ruang guru dan duduk di meja kerjaku. Kebetulan sedang tidak ada jam mengajar. Tiba-tiba, datang sebuah kabar tentang pemerintahan baru yang akan mengubah kebijakan pendidikan. Isu-isu itu berembus kencang di kalangan para guru. Ada yang optimis, berharap kebijakan baru akan membawa perubahan positif. Namun, tak sedikit pula yang pesimis.
“Apa lagi yang akan berubah? Apakah status kami akan diperbaiki?” gumamku saat berdiskusi dengan sesama guru PPPK.
Wajah-wajah mereka tampak cemas, seolah memendam beban yang sama. Tak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Hanya waktu yang akan menunjukkan bagaimana nasib kami selanjutnya. Aku membiarkan tanyaku menggantung tanpa jawaban.
Aku kembali teringat pada sebuah momen ketika Fauzi mengajak rekan-rekan guru untuk menulis bersama. Kala itu, ia mengundang beberapa guru PNS untuk mengikuti lokakarya kecil yang ia adakan. Namun, hanya segelintir yang datang. Sisanya menganggap menulis sebagai pekerjaan yang tak penting.
“Kami sudah sibuk mengajar, mana sempat menulis,” ujar salah satu guru dengan nada setengah meremehkan.
Fauzi hanya tersenyum tipis mendengar ucapan itu. Tak ada gunanya berdebat. Baginya, mengajak orang lain untuk menulis memang bukan hal yang mudah. Dibutuhkan kesadaran dan keinginan dari dalam diri masing-masing. Maka, ia memutuskan untuk terus menulis sendiri meskipun tanpa dukungan penuh dari rekan-rekannya.
Pagi ini, ia kembali cerita padaku setelah dipanggil kepala sekolah dan diminta menghadap ke ruangannya.
“Kepala sekolah memintaku untuk melibatkan lebih banyak guru dalam kegiatan menulis dan menerbitkan buku. Beliau berharap, mungkin dengan begitu, kesadaran terhadap pentingnya menulis bisa meningkat,” ucapnya.
Aku mengerti maksud kepala sekolah. Namun, mengajak guru lain bukanlah perkara mudah. Sudah berkali-kali ia mencoba, namun hasilnya selalu sama. Tapi, ia tak ingin menyerah. Ia memutuskan untuk mencoba cara yang berbeda.
Aku merasa lega. Di balik sikap kritisnya, ia masih berjuang untuk orang lain. Bahkan, sedikit memikirkan dirinya sendiri. Aku sadar, perjuangan seorang guru tak hanya sebatas mengajar di dalam kelas. Lebih dari itu, seorang guru harus mampu menjadi teladan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Semua itu aku temukan dalam diri Fauzi.
Di akhir hari, aku melihatnya duduk sendirian di ruang kelas yang kosong. Pandangannya menerawang jauh, membayangkan masa depan yang lebih baik. Aku tahu, jalan yang ia tempuh masih panjang dan penuh rintangan. Namun, ia tak gentar. Selama ia masih bisa menyalakan semangat dalam dirinya, ia akan terus melangkah.
“Oh, lingkungan guru akan rasakan kebijakan lagi. Oligarki,” gumamku setelah mendengar beberapa isu terkini tentang perubahan pendidikan.
Aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Perubahan pendidikan sebagai dampak dari pemerintahan yang baru adalah keniscayaan. Aku hanya bisa meyakini tekad yang sudah ditunjukkan oleh Fauzi. Selama terus berkarya, guru akan tetap menjadi pelita yang menerangi jalan ilmu bagi para siswanya.
Aku masih mengamatinya. Ia kembali menulis. Bukan sekadar menulis, tapi menuangkan harapan dan doa dalam setiap kata yang ia rangkai. Bagi dunia luar, mungkin ia hanyalah seorang guru biasa. Namun bagi para siswanya, ia adalah sosok yang luar biasa. Sosok yang tak pernah lelah menyalakan semangat meski di tengah gelapnya realitas yang harus dihadapi.
Aku tahu bahwa perjuangan Fauzi belum usai. Setiap langkah kecil yang ia lakukan akan membawa perubahan besar suatu hari nanti. Jika Tan Malaka pernah bilang bahwa idealisme menjadi kemewahan terakhir, itu berlaku bagi Fauzi. Ia berdiri di atas idealismenya. Meskipun tidak harus memaksakan semua idealismenya terpenuhi, ia merasa kaya dan bahagia.
Bionarasi
Sahari Nor Wakhid, Guru SMP Negeri 5 Sangatta Utara, Kutai Timur. Mulai menekuni dunia kepenulisan sejak tahun 2020. Telah menerbitkan 9 buku solo dan 43 antologi bersama. Buku paling mutakhirnya adalah Selebrasi (Kumpulan Cerpen, 2025). Bisa dikontak melalui IG @saharienwe