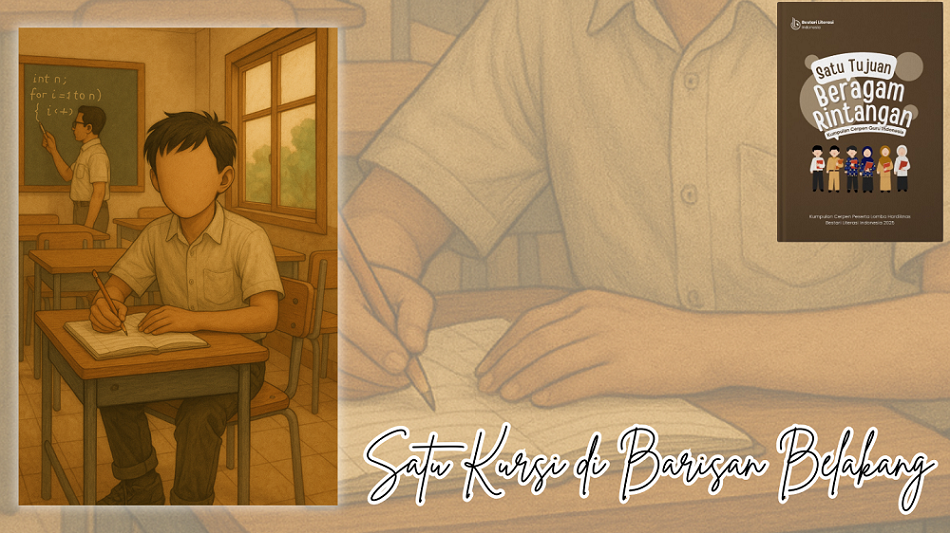Namanya Bintang. Seorang anak laki-laki yang selalu duduk di barisan paling belakang, dekat jendela. Ia datang ke sekolah dengan baju yang warnanya mulai pudar dan sepatu yang mulai menganga di ujung. Tapi sorot matanya tajam. Ada semangat aneh yang terpancar dari caranya mencatat, dari caranya menatap papan tulis seakan setiap huruf di sana adalah petunjuk hidup.
Aku, guru yang mengajarnya di kelas sebelas. Bukan guru pertama yang mengenalnya, tapi mungkin satu dari sedikit orang yang memperhatikannya lebih dekat. Ia tak banyak bicara, tapi nilai-nilainya diam-diam mendekati sempurna. Tidak pernah terlambat, tidak pernah membuat masalah, namun juga tidak pernah mengangkat tangan saat kutanya.
Suatu hari, aku menghampirinya saat jam istirahat.
“Bintang, kamu suka pelajaran informatika, ya?”
Dia hanya mengangguk pelan. Lalu, untuk pertama kalinya, ia menjawab.
“Informatika tidak mengharuskan saya bicara banyak, Pak. Cukup berpikir runtut dan menulis kode yang jelas. Rasanya seperti berbicara dengan mesin yang benar-benar mendengarkan.”
Jawaban itu seperti tamparan halus. Aku guru, tapi aku lupa bahwa tidak semua anak nyaman dengan dunia ramai. Sejak hari itu, aku mulai membangun jembatan pelan-pelan. Lewat catatan di kertas ulangan, lewat senyuman singkat saat bertemu di lorong sekolah. Tidak mendesak, tidak menuntut. Hanya hadir.
Ia mulai terbuka. Tidak dengan banyak kata, tapi dengan tanda-tanda kecil. Ia pernah menyelipkan coretan rumus di kertas tak bertuan, diletakkan di meja guru. Bukan untuk dinilai, hanya untuk dibaca. Ia juga mulai datang lebih awal ke kelas, duduk tenang membuka buku sebelum bel tanda masuk berbunyi. Semua ia lakukan dalam diam, tapi terasa seperti suara keras bagi yang ingin mendengar.
Hingga suatu pagi, Bintang tidak hadir. Satu hari. Dua hari. Seminggu.
Aku khawatir, dan mencari tahu ke wali kelasnya. Tak ada kabar pasti, hanya informasi samar bahwa keluarganya sedang mengalami kesulitan. Aku tak tahan hanya menunggu. Maka, aku putuskan untuk datang ke rumahnya. Dengan alamat seadanya dari data sekolah, aku menempuh jalanan berlubang menuju sebuah dusun di pinggir kecamatan.
Rumahnya kecil, berdinding papan, dengan atap seng yang sebagian sudah karat. Ibunya menyambut dengan senyum lelah. Bintang sedang demam, kata beliau. Ayahnya bekerja serabutan di luar kota, dan penghasilan mereka nyaris tak cukup untuk makan, apalagi biaya berobat.
“Apa Bintang masih ingin sekolah, Bu?” tanyaku pelan.
Ibu Bintang menunduk. “Ia tidak pernah berhenti belajar, Pak. Tapi katanya, kalau terus sekolah, dia takut bikin beban.”
Aku diam, menatap bocah itu dari sela tirai. Tubuhnya terbaring, kurus, dengan buku pelajaran masih di sisi.
Dalam perjalanan pulang, aku berpikir panjang. Apa arti “guru untuk negeri” kalau tak bisa menjangkau satu anak yang tengah bertaruh antara pendidikan dan perut kosong?
Malam itu, aku menulis surat ke kepala sekolah. Aku usulkan agar Bintang dibebaskan dari iuran. Aku hubungi teman-teman guru untuk menggalang donasi sederhana. Aku bahkan mengajukan program belajar dari rumah secara berkala untuk anak-anak yang terancam putus sekolah.
Sebagian mendukung. Sebagian mempertanyakan. Tapi aku tidak mundur.
Beberapa bulan ke depan menjadi masa penuh harap. Setiap kali membuka absensi kelas, mataku otomatis meluncur ke baris nama “Bintang”. Kadang hadir, kadang tidak. Tapi ia selalu mengumpulkan tugas, entah lewat teman, atau titipan yang diam-diam diletakkan di meja guru. Ada sesuatu yang membuatku tak bisa menyerah pada anak ini, seperti melihat bunga kecil tumbuh di celah batu.
Dua minggu kemudian, Bintang kembali ke sekolah. Wajahnya pucat, tapi ada senyum tipis yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia duduk di kursinya yang biasa, barisan paling belakang. Dan saat kutanya soal materi sebelumnya, ia menjawab dengan suara pelan, tapi mantap.
Aku tidak menangis saat itu. Tapi ada sesuatu yang hangat menetes di dalam dada.
Hari-hari selanjutnya, Bintang tidak lagi sekadar bayangan di pojok kelas. Ia mulai menulis lebih banyak, kadang mengajukan pertanyaan melalui kertas, dan sesekali menungguiku setelah pelajaran hanya untuk menunjukkan jawaban alternatif dari soal yang kuberikan. Aku tahu, ia tidak hanya belajar demi nilai. Ia belajar karena itu satu-satunya cara ia bertahan. Belajar adalah bentuk keyakinannya bahwa hidup bisa berubah.
Bertahun-tahun kemudian, saat aku sudah bukan lagi guru tetap, sebuah surat datang ke rumahku. Sampulnya rapi, dengan kop universitas ternama di dalam negeri. Di dalamnya, ada tulisan tangan yang kukenal:
“Pak, saya lulus sebagai lulusan terbaik. Saya kuliah dengan beasiswa penuh. Terima kasih sudah melihat saya, bahkan saat saya sendiri hampir menyerah melihat diri saya. Saya ingin menjadi guru, seperti Bapak. Agar satu kursi di barisan belakang tidak pernah lagi luput dari perhatian.”
Aku membaca surat itu berulang kali. Setiap kata terasa seperti hadiah. Di dunia yang sering lupa pada mereka yang sunyi, Bintang adalah suara dari barisan paling belakang yang akhirnya didengar.
Namanya Bintang. Tapi bagiku, dia lebih dari itu, dia adalah pengingat bahwa seorang guru tidak hanya mengajar di depan kelas, tetapi juga menjangkau hati yang tersembunyi di sudut-sudut ruang. Bahwa menjadi guru untuk negeri, artinya hadir untuk satu anak sekalipun, karena dari satu anak, bisa lahir masa depan yang tak kita duga.
Kini, setiap kali aku memasuki ruang kelas baru, aku selalu melirik kursi-kursi di barisan paling belakang lebih dulu. Barangkali di sana ada lagi seorang Bintang yang lain. Seseorang yang tampak diam, tapi sebenarnya sedang berteriak lewat caranya bertahan. Aku belajar bahwa tidak semua perjuangan terlihat jelas. Sebagian terbungkus dalam sunyi, dalam sorot mata yang menyimpan harapan.
Dan tugas kita, para guru, adalah menemukannya sebelum mereka hilang tanpa jejak.