Sudut Pandang
Karya: Solu Erika Herwanda
Siang itu lagu Broken Angel berdentum-dentum di kafe Kitakini. Terdengar seorang perempuan membujuk pelayan agar mengecilkan volume musik kafe. Tak sengaja aku melihat sang pelayan tersenyum kegirangan. Mungkin karena perempuan itu memberikan tip yang pantas untuknya. Terbukti, beberapa saat setelahnya volume musik kafe mulai mengecil.
Sesekali kulempar pandangan ke arah perempuan itu. Perempuan itu lantas memakai earphone dan berbicara ala seorang presenter. Kalau diperhatikan lagaknya, ia sedang menjadi moderator sebuah webinar. Aku terkikik ketika sadar ternyata aku sudah tak ingat kapan terakhir kali ikut webinar dan kelas daring.
Layar laptopku masih tugur di beranda menu utama. Kursor di layar naik turun. Kugerakkan tanpa berniat membuka satu aplikasi pun. Ini kulakukan semata agar orang-orang tak memandangku sebagai perempuan gabut yang numpang wifi di Kafe Kitakini.
Terjarak dua meja kosong di depanku, Agnesia berada. Sahabatku itu masih betah bergelayut di lengan Bima. Mereka semacam tak punya kegiatan lain kecuali berkencan di kedai kopi, menonton bioskop, dan menyaksikan konser musik pantura. Di kota yang cukup padat penduduk ini, aku, barangkali juga Agnesia tak punya pilihan lain kecuali berenang menyusur arus di mana kami hidup.
“Cromboloni with choco chips and sprinkle, dan matcha cheese icenya, Kak,” ucap seorang perempuan seusiaku dengan senyum ramahnya yang tampak dipaksakan.
“Terima kasih,” Aku menimpali sebelum ia hilang di balik meja kasir.
Ponselku bergetar. Panggilan dari Mama. Buru-buru kuangkat ponsel dari meja, kugeser ikonik ponsel warna merah ke atas, selepasnya aku bergegas ke roomchat.
[Reana masih ada kelas, Ma. Nanti Reana telepon lagi.]
Centang dua. Biru. Mama mengetik. Balasannya sampai.
[Oh ya, selamat belajar Cah Ayu.]
Kubiarkan pesan itu sebelum data seluler kumatikan. Melirik jam tangan digital ini, lebih kurang tiga puluh menit sudah aku menunggu. Mungkin ini menjadi hal biasa di kafe Kitakini. Semuanya serba lambat. Mulai dari pelayan itu memasak menu pesanan, menyusun pesanan ke baki hingga saat kafe ini diperuntukkan menunggu seseorang.
Aku memejam. Menyingkirkan segala pikiran buruk kepada Alan. Sekejab kemudian, kecupan kecil mendarat di pipiku.
“Aku dikejar-kejar polisi Ay. Tapi untungnya lolos. Aku nerobos lampu merah, takut bikin kamu nunggu lama eh malah dikejar polisi. Aku nggak lihat kalau ada razia, Ay.” Alan menjelaskan di sela napasnya yang berbenturan.
“Santai saja. Biasanya juga kau tak pernah tepat waktu.”
“Marah?”
Aku diam saja. Enggan menanggapi. Alan bertanya lagi.
“Kamu udah pesenin aku, kan?”
Aku hanya menggeleng. Masih enggan menjawabnya .
“Pinjem dulu seratus ya, aku belum ada.”
Aku bilang tak punya. Alan naik pitam dan menggebrak meja. Mataku terpaku pada wajahnya yang mulai merah. Entah karena marah atau malu. Aku mengamati sekeliling, orang-orang memerhatikan kami. Termasuk perempuan moderator tadi juga menoleh sesaat ke arah kami. Sadar apa yang kami lakukan ini menganggu orang-orang di kafe, aku keluar. Alan berteriak dan menyusulku. Agnesia dan Bima juga melihat pertengkaran kami, aku dengar Agnesia memanggil tapi kuabaikan. Aku terus saja menuju pintu keluar. Seorang penjaga pintu mengamati kami dan tersenyum canggung.
“Maksud kamu apa sih, Re?”
Sampai di parkiran, Alan menahan tanganku. Ia kembali memakiku. Ia mengancamku untuk putus, ia pikir aku akan seperti sebelumnya yang melunak setelah ia bilang putus. Namun ia salah. Kali ini, aku telah benar-benar muak dengan segala sikapnya.
“Iya. Kita putus. Lupain aja uang-uangku yang ada di kamu.”
Wajah Alan kini nyaris pucat. Aku meninggalkannya. Semenjak saat itu, kami lost kontak. Di kampus, aku tak pernah lagi papasan dengannya atau melihat cepak rambutnya. Agnesia terus menerorku dengan pertanyaan mengapa, ada apa, kenapa bisa sampai aku dan Alan putus. Sementara aku tak ingin mengungkitnya. Meski aku tahu, Agnesia menyimpan kesal karena ini. Aku juga sering menolak ajakannya bolos beberapa hari setelah itu. Aku tak berselera untuk bolos dan menuruti kemauannya. Sejak itu, Agnesia dan aku jarang jalan bersama lagi.
***
Aku masuk ruang kelas. Hari ini UAS terakhir dan aku terlambat. Ketiduran. Mengebut tugas semalaman bikin mataku bengkak dan mencuri waktu sebelum kuliah untuk tidur, sialnya justru aku kebablasan dan telat.
Profesor Yamin menatapku tajam. Tatapan menghujam. Aku meminta maaf atas keterlambatan. Namun yang tak pernah kuduga, aku tak bisa masuk kelasnya dan ikut UAS. Bukan soal terlambat saja, melainkan aku telah lebih dari lima kali melewatkan matkulnya. Maka, tak ada nilai untukku. Aku harus mengulang tahun depan, katanya. Itu terjadi bukan pada matkul Profesor Yamin saja, sebelumnya telah ada empat matkul lainnya yang harus kuulang.
Di bangku taman depan fakultas ekonomi aku duduk melamun. Bayangan Mama memenuhi kepalaku. Toko roti Mama, senyum mendiang Papa yang menitipkan Mama dan bisnis rotinya. Celetuk kaprodi yang baru kudengar menyelinap diam-diam di antara Mama, toko rotinya, dan pesan mendiang Papa.
“Lunas UKT tidak bisa mengubah keputusan beberapa dosen, apalagi menambal absen Anda yang bolong. Anda tetap harus mengulang, Reana.”
Sebuah notif pesan dari Mama.
[Uang bulanan kamu masih cukup, Nduk?]
Aku tak langsung membalas. Kulihat dompet elektronik. Tiga ratus ribu sekian, cukup untuk sekitar tiga hari kedepan. Itu pun aku harus sangat hemat. Kuhela napas panjang dan kembali ke roomchat.
[Nduk?]
Aku membalasnya, [Masih cukup, Ma. Tenang saja.]
Entah sudah berapa sering aku berbohong pada Mama, tapi kali ini kupikir kebohongan yang baik.
[Kalau enggak cukup bilang ya, Nduk. Jangan berbohong.]
Hatiku menghangat. Air mataku meluncur perlahan.
[Iya, Ma. Masih cukup kok.]
Aku meninggalkan kampus dan kali ini kukunjungi lagi kafe Kitakini. Kafe itu lengang. Ada Agnesia dan Bima di pojok kafe, tapi mereka tak tahu kehadiranku. Beberapa barista yang sedang mengobrol menyiapkan diri menyapaku.
“Silakan, Kak,” ucap salah satunya dengan wajah ramah yang dibuat-buat.
“Apa lowker di sini sudah terisi, Kak?” kataku melirik kertas yang ditempel di tembok kasir; Dicari Karyawan/Karyawati.
“Belum sih, Kak. Tapi posisi yang dicari itu tukang bersih-bersih.” Barista itu memandangku ragu. Sepertinya ia berusaha menjaga agar aku tak tersinggung.
Aku tak masalah dan seketika menyepakati kerjaan itu. Setelah beberapa alasan salah satunya karena aku pelanggan setia, pemilik kafe memberi toleransi agar jam kerjaku tidak bersinggungan dengan jadwal kuliah.
***
Pagi ini Mama datang tanpa kabar sebelumnya. Aku menelan ludah melihat ekspresi Mama yang tampak akan protes dengan apa yang kulakukan.
“Reana ….”
“Cleaning service?”
Aku menyilakan Mama duduk. Kuceritakan bahwa aku ingin hidup mandiri. Makan dengan hasil kerjaku sendiri. Selama aku menjelaskannya, aku tak tahu arti tatapan Mama. Mungkin Mama iba atau bisa jadi justru kecewa. Namun, baik ataupun tidak respons Mama, aku tetap tidak akan resign.
“Tapi kuliahmu aman, kan, Nduk?”
“Aman, Ma.”
“Tahun depan kamu wisuda, kan Nduk?”
“Ada beberapa matkul Reana mengulang. Mungkin wisuda Reana mundur, Ma.”
Aku menunduk. Aku yakin Mama akan murka setelah ini.
“Mama enggak menyangka,” tegasnya.
“Mama bangga, Nduk.” Ia menggenggam erat jemariku. Keningku mengerut, Mama meneruskan ucapannya, “Mama bangga kamu itu enggak bohong sama Mama.”
Aku makin terdiam.
“Baru-baru ini Mama tahu berita, orang tua yang dibohongi anaknya. Ngakunya kuliah, pas wisuda dan orang tuanya datang, dia ternyata enggak pernah kuliah. Mama enggak bisa bayangin kalau kamu juga bohongin Mama begitu.”
Penjual bubur ayam di perempatan lewat di depan kosku dan memasukkan gerobak ke depan kosnya.
“Astaga, Ma. Reana berangkat kerja dulu. Udah pukul delapan lebih, Ma. Mama enakin aja, ya. Ada banyak makanan Reana di kulkas. Daaa Mama!”
Aku melajukan motor dengan kecepatan sedang. Terbesit ucapan Mama yang berlebihan terhadapku. Mama tidak perlu tahu yang telah lalu. Mama hanya berhak tahu tatanan hidupku yang baru (*)



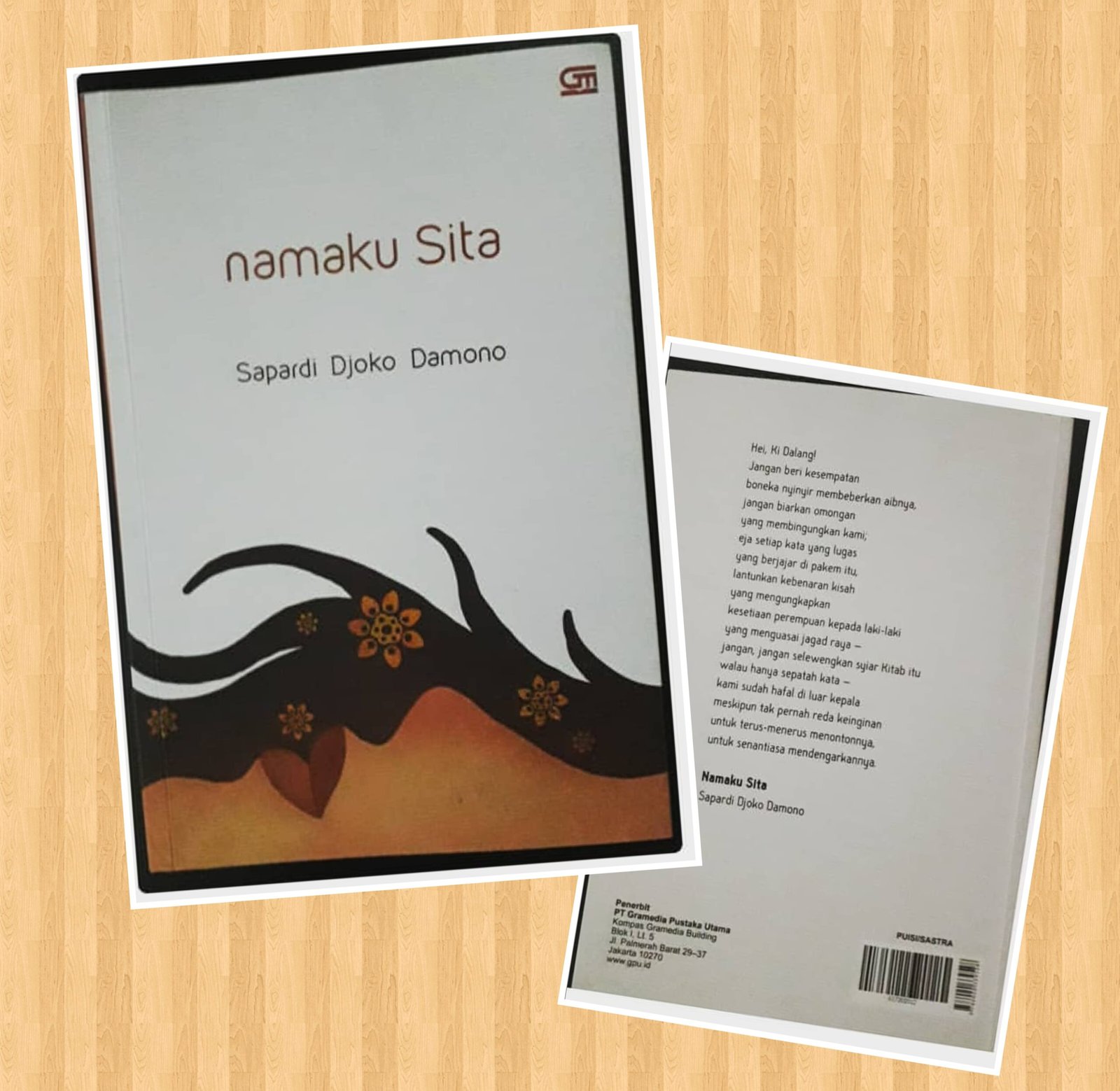






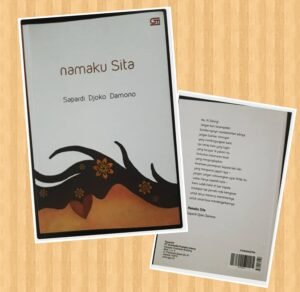
29 Responses
Keren kereenn..
Fighting
Suka banget sama cerpennya.
keren!
Ah, paragraf tetakhirnya mirip diriku, hehehe ….
Cerita yang menarik karena cukup dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari. Disajikan dalam sebuah judul bertajuk “Sudut Pandang” memberikan titik fokus pada bagaimana pandangan orang terhadap sesuatu dan pentingnya kejujuran.
Kerenn
Cerita yang bagus, keren, menarik. Selain memberikan sesuatu tentang hal kejujuran, dari sini kita belajar tentang kemandirian dan ketangguhan dalam melewati kehidupan sehari-hari, seperti apa yang dilakukan Reana.
Salah satu cerita yang emang sering terjadi saat kuliah. Banyak dilemanya, hehehe….
Wah cerpennya rapi dan bagus banget! Relate dengan kehidupan sehari-hari. Good luck buat Kak Solu 🙂
Selalu keren
Menarik 😁
Daebakkk!!! Hwaiting Mbak Sholuuu👍👍👍😊
Ngga ekspeks sih kalo endingnya gituu, seruu 😁
Ceritanya cocok banget buat anak muda Indonesia. Bahasanya juga mengalir. Midah dipahami. Keren.
Keren. Jadi penasaran kelannutan ceritanya😁
Bener bener ya..Kak Solu.. btw ada pinjemduluseratusnya.. jadi ingin belajar lagi ke Kak Solu..Mengaitkan dengan apa yang terjadi di sekitar saat ini. Kereren
Cerpenmu seperti kisahnya Sol. Keren bangett lohhh. Semangat terus ya….Makin perbanyak karyamu
Sukak🤭☺️
Wow this is really amazing soku… semangat yak jangan lupa tingkatin terus buat karyanya… wish u all the best😘
Keren!
Suka alur ceritanya 😙💪
Bagus kak cerita 😍
Kerenn!!
Terus berkarya kak!
keren bangettt!
keren banget kaaa
Nice! Jadi terkenang masa kuliah.
Menginspirasi
Sip