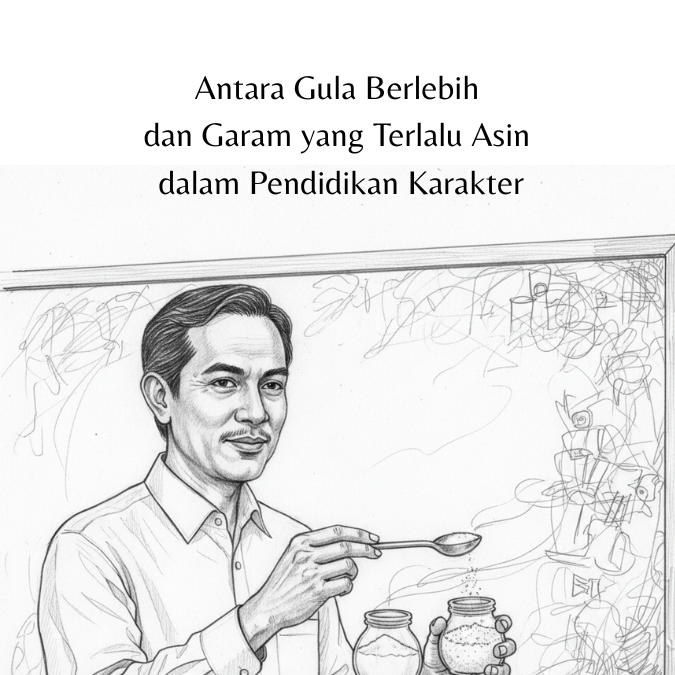Oleh: Luthfi Azizan
Musim ajaran baru selalu membawa aroma debu kapur yang harum dan semangat guru yang, kita akui saja, seperti bara api yang terlalu besar di tungku kecil. Mereka ingin anak didiknya menjadi yang terbaik, yang paling berkarakter, yang paling siap mengguncang jagat raya. Namun, seperti memasak hidangan istimewa, niat tulus saja tidak cukup. Dibutuhkan sendok takar dan ketelitian seorang seniman.
Di tengah gegap gempita obsesi pendidikan karakter ini, kita kini menyaksikan sebuah ironi yang menjebak: Kita telah membagi metode pengasuhan menjadi dua klan ekstrem.
Klan pertama adalah Pemuja Gula Berlebih. Mereka meyakini bahwa hanya dengan pujian, hadiah, dan pelukan tanpa henti karakter emas bisa ditempa. Klan kedua adalah Pencinta Garam Terlalu Asin. Mereka yakin bahwa disiplin hanya tumbuh dari hukuman keras, bentakan lantang, dan suasana tegang bak barak militer.
Kita membajak sekolah dengan cinta yang keliru. Sekolah yang seharusnya menjadi kebun bunga, kini terancam oleh dua bencana rasa: kemunafikan yang manis atau kepatuhan yang getir.
Kisah Tragis Si Pecandu Gula: Malaikat Bertubuh Manja
Di ruang kelas yang dipenuhi stiker bintang lima dan piala berkilauan, kita sedang menciptakan generasi “Pencari Gula”. Setiap tarikan napas, setiap keberhasilan kecil—bahkan sekadar meletakkan pensil di tempatnya—diganjar tepuk tangan meriah.
Kita telah mengubah apresiasi menjadi suap ekstrinsik. Anak-anak tidak lagi rajin dan jujur karena itu adalah kebaikan yang inheren, melainkan karena mereka mendamba reward instan: stiker bergambar senyum, cokelat kecil, atau pujian di linimasa media sosial sekolah.
Ironisnya, saat dunia nyata—yang tak punya stok piala tak terbatas—menampar mereka, jiwa mereka serapuh biskuit yang basah. Mereka kehilangan resiliensi. Mereka tak tahan kritik. Sedikit ketidaknyamanan dianggap sebagai akhir dari semesta.
Kita memberi mereka begitu banyak gula hingga daya juang mereka mengidap diabetes. Karakter yang seharusnya mandiri dan kuat, tumbuh menjadi malaikat bertubuh manja, yang hanya bisa terbang jika didorong oleh angin tepukan tangan.
Jeritan Pilu dari Dasar Garam: Kepatuhan yang Dibungkam
Di seberang spektrum, berdiri benteng Garam Terlalu Asin. Di sana, hukuman fisik atau verbal yang menampar harga diri masih dianggap sebagai pupuk kedisiplinan. Kata-kata keras dilemparkan tanpa peduli bahwa hati seorang anak bukanlah kulit badak.
Pendidik dari klan ini lupa: Hukuman yang keras dan memalukan hanya menumbuhkan dua hal pada diri siswa: kebencian tersembunyi dan kepatuhan palsu. Siswa akan menjadi patuh, tentu saja, tetapi bukan karena kesadaran, melainkan karena ketakutan pada sanksi. Mereka seperti robot yang bekerja optimal hanya saat sensor mata guru mendeteksi mereka.
Kreativitas adalah korban pertama yang mati di lingkungan yang asin dan kaku. Kenakalan yang seharusnya menjadi sinyal kebutuhan atau luapan energi, dipangkas habis dengan sanksi yang membekukan. Bagaimana mungkin karakter yang kuat bisa tumbuh dari jiwa yang selalu dibayangi rasa cemas dan takut? Pendidikan macam ini hanya menghasilkan pembangkang yang tertunda.
Seni Menakar Bumbu: Mencari Titik Gurih di Kelas
Lalu, di mana letak keindahan pendidikan karakter itu?
Jawabannya bukan pada Gula atau Garam. Jawabannya ada pada sendok takar yang bijaksana dan umpan balik yang tulus.
Ganti Gula dengan Rempah Spesifik: Kita harus pindah dari hadiah materi ke apresiasi yang fokus pada proses. Alih-alih berkata, “Kamu hebat!“, katakanlah, “Saya bangga melihat kegigihanmu kembali mencoba soal itu setelah tiga kali gagal.” Kita menghargai perjuangan, bukan sekadar hasil. Ini adalah Cinta yang Mendewasakan.
Ganti Garam dengan Konsekuensi Logis: Hukuman harus dicabut dari kamus dan diganti dengan konsekuensi logis yang mendidik. Jika siswa merusak properti, konsekuensinya adalah memperbaiki atau menggantinya—bukan dihukum berdiri di depan kelas. Ini mengajarkan tanggung jawab, bukan trauma.
Pendidik yang arif adalah seorang Juru Masak Karakter yang handal. Ia tahu kapan harus memberi senyum sebagai rempah penyemangat, kapan harus diam sebagai waktu refleksi, dan kapan harus memberi konsekuensi sebagai penyeimbang rasa.
Maka, mari kita ambil kembali sendok takar itu, wahai para pendidik. Pendidikan karakter sejatinya adalah seni yang elegan. Mari kita ciptakan masakan karakter yang gurih: tidak terlalu manis hingga memuakkan, tidak pula terlalu asin hingga menghanguskan. Karena di antara kedua ekstrem itulah, jiwa yang berani dan berprinsip akan menemukan takdirnya. Wallahu a’lam bishawab
Subang, 20 November 2025