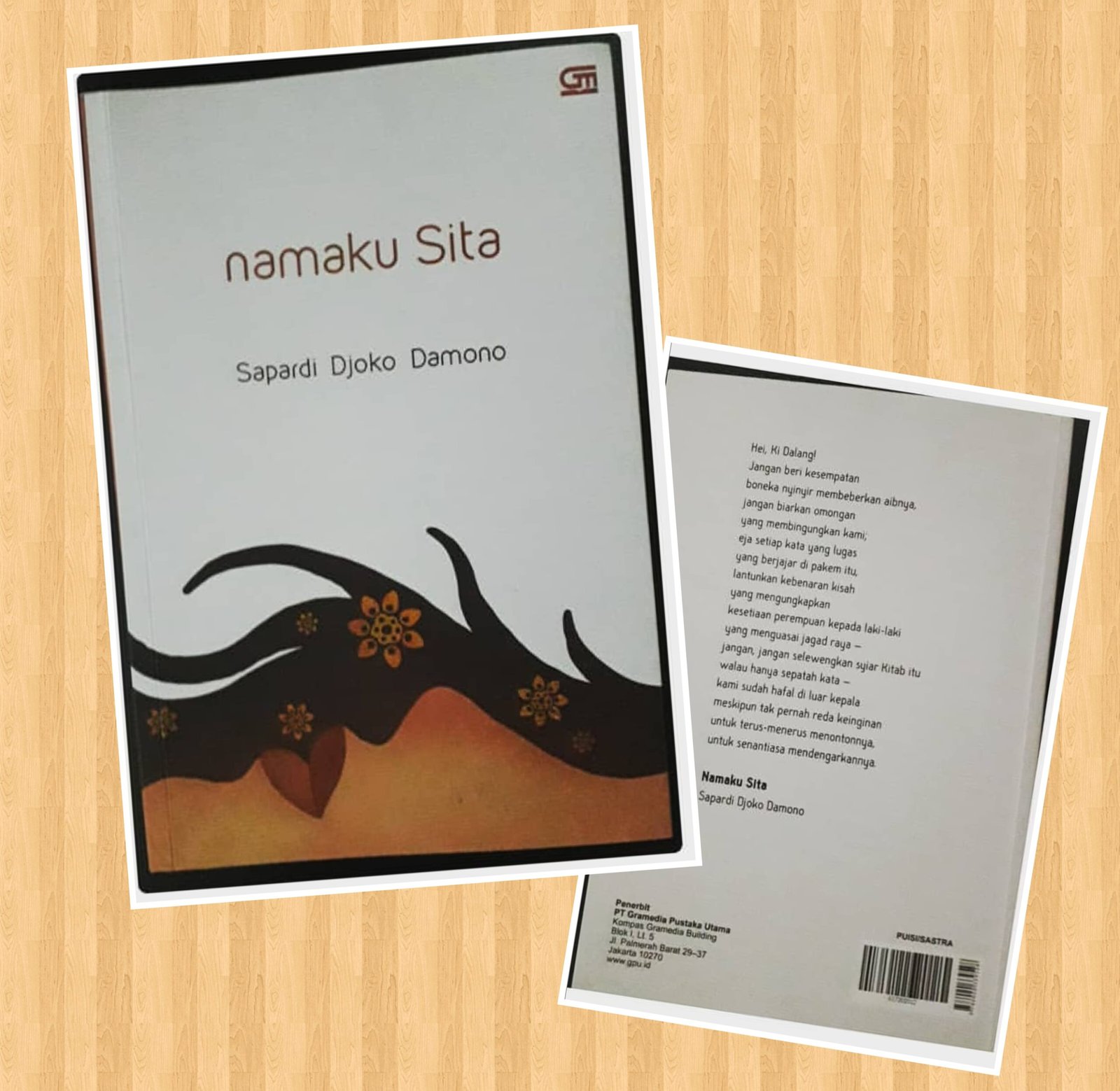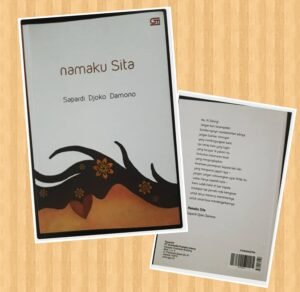Kisah dalam Selimut Hujan
Karya: Ferisa Lestari Nugrahayu, S.Si
Ruangan serba oranye itu terasa lebih dingin dari biasanya. Kunaikkan suhu AC, dan kumatikan kipas-kipas yang seharian menyala menghalau hawa panas. Kini, hujan turun. Deras dan berangin kencang. Suhu yang semula panas mulai terjun bebas, dan kami mulai merapatkan jaket masing-masing.
Suara para siswi melengking saat mereka beramai-ramai berlarian dari kolom parkir ke ruang utama. Gadis-gadis itu mengibas-ngibaskan rok-rok seragam mereka yang basah, sambil menenteng plastik-plastik berisi seblak pedas, dimsum kukus hangat, dan bakso panas.
“Wah, baunya enak banget!” aku spontan berujar.
“Pak, anginnya seram!” salah seorang dari mereka mengadu, disusul teman-temannya yang lain, bersahutan mengeluh soal hujan dan hawa dingin.
Salah satu di antara mereka tiba-tiba berseru heboh, ingat bahwa helmnya masih tergantung di motor. Dia melempar semika dimsum ke meja dan berlari mengevakuasi helmnya. Aku ikut berlari menyusul sambil menyambar payung umum dekat pintu keluar. Kulindungi siswi itu.
“Makasih Pak Jun!” ucapnya ceria sambil menenteng helm.
“Sama-sama, Lely!” aku meniru nada bicaranya, membuat Lely tertawa.
Saat kami kembali, siswi-siswi lain sudah menjejali kursi-kursi, bersahutan dengan suara penuh semangat. Mereka mengulang cerita tentang pelanggan menyebalkan di warung seblak, atau barista kafe depan yang ganteng, sambil memakan makan siang masing-masing. Aroma bumbu dan kuah menguar.
Riuh para siswa dan bau-bauan makanan ini adalah salah satu hal yang paling membekas selama aku mengajar di bimbingan belajar ini. Apalagi jika hujan deras turun, udara menjadi sejuk, dan makanan berkuah mendadak menjadi dua kali lebih enak. Suara-suara para siswa bersaing dengan deru air, terasa lebih seru.
Aku duduk di kursi khusus pengajar di pojok ruang, menikmati suara yang akan kurindukan sebelum mereka lulus ini.
“Nay, teman-teman cowok ke mana? Nggak les hari ini?” aku bertanya—setengah berteriak— pada Nayla yang duduk paling dekat denganku.
“An owok usal!” dia menjawab dengan mulut masih setengah penuh. Ditelannya bakso-bakso itu dengan agak susah payah sambil menutup mulut. “Anak-anak cowok futsal,” ulangnya, “nanti datang telat.”
“Sudah hampir ujian SNBT masih sibuk futsal ya?” aku berkomentar. Gadis-gadis itu berbalik, berseru setuju. Hyra yang duduk di meja terujung langsung berseru, mengadu bahwa Lingga—pacarnya—lebih memilih ikut pertandingan futsal daripada membenahi skor try out ujian masuk perguruan tingginya yang pas-pasan. Windri di ujung meja yang satu menyambung, mengeluhkan skornya sendiri, dan kesulitan belajar subtes tertentu. Beberapa menyahut mengiyakan.
Aku menumpukan dagu ke telapak tangan, menyimak aduan dan cerita-cerita mereka yang semakin lama semakin seru. Sesekali aku tertawa dan merespons, memberi validasi pada kekesalan-kekesalan mereka, menciptakan suasana bergosip yang menyenangkan.
“Pak Jun itu kalau bergosip sama cewek-cewek sudah pro,” komentar Kalina, penanggung jawab akademik bimbel yang sudah hafal kebiasaanku di luar jam mengajar. Aku hanya tertawa, dan berkata dalam hati, bukankah memang begitu seharusnya seorang pengajar? Memberi ruang aman dan nyaman bagi siswa-siswanya untuk bercerita dan bercengkerama. Sesuatu yang mungkin tidak selalu bisa dilakukan guru-guru di sekolah formal.
Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Waktu bimbingan belajar akan dimulai setengah jam lagi, dan para siswi sudah kehabisan makanan dan bahan gosip. Mereka masuk ke dalam fase kantuk pasca makan siang yang familiar.
Siswi-siswi dengan seragam setengah basah itu akan menyandarkan kepala ke meja, tembok, atau ke bahu kawan-kawan mereka, menahan kantuk sambil menggulung layar ponsel. Sesekali mereka mengomentari video TikTok, dan kawan-kawan mereka menjawab dengan suara lesu. Perut kenyang benar-benar menurunkan energi mereka. Ditambah udara sejuk dan gemuruh hujan, kantuk benar-benar sukar ditahan.
Aku sendiri ikut menguap. Tidak ada yang menarik di ponsel, jadi aku memutuskan untuk keluar mencari makan. “Kalina, aku keluar sebentar ya,” aku berpamitan sambil menyambar payung umum yang ditaruh di tong rotan.
Hujan ini benar-benar deras. Hawanya dingin dan empasannya keras. Aku agak menyesal tidak mengambil payung yang lebih besar. Bajuku yang tadi sudah terciprat di sana-sini, sekarang semakin lembab. Pandanganku juga buram di tengah guyuran air, jadi kuputuskan untuk menepi ke teras minimarket terdekat.
Dia ada di sana. Seorang anak laki-laki berseragam setengah basah. Perawakannya kecil, dan kacamatanya kebesaran, merapat di dinding kaca, di antara tumpukan galon dan tabung gas merah jambu.
“Lun!” aku menyapa, mengenali dia sebagai muridku di bimbel, Ralunda Kristanoba. Kelas 12 jurusan IPA. Dia kerap diejek karena namanya yang aneh dan sosoknya yang kelewat pendiam. Dia mengangguk sopan, membalas sapaanku.
“Kamu nggak ikut futsal?” suaraku bersaing dengan suara hujan. Dia menggeleng.
“Mau berangkat les? Yuk, bareng saya!” ucapku, mengira dia terjebak hujan di sini.
Lunlun—panggilan kesayangan teman-temannya—menggeleng. Dia tidak bicara, tetapi dari gesturnya terlihat tidak nyaman. Belum sempat aku berkata apa-apa, dia sudah beranjak pergi dengan payungnya sendiri. Sosoknya seperti tenggelam di dalam payung besar itu.
Aku menceritakan perihal Lunlun ini kepada Jovan dan Hari, dua pengajar lain yang tengah berkumpul di ruang guru. Kalina juga ikut bergabung setelahnya. Kami duduk melingkar di sofa, serius bicara.
Aku baru tahu bahwa Lunlun memang sudah beberapa kali tidak masuk les. Mamanya bilang, Lunlun selalu berangkat les, tapi saat kami cek, presensi digitalnya kosong. Aku jadi mengingat-ingat, Lunlun memang sudah lama tidak terlihat di kelasku sendiri.
“Nilai try out SNBT Lunlun kurang tinggi,” Kalina berkata pelan, “Mamanya ngotot Lunlun harus masuk fakultas kedokteran. Mamanya ngotot pokoknya anaknya sudah berangkat les, dan malah marah-marah ke kita, bilang kalau seharusnya kita yang bertanggung jawab atas Lunlun.”
“Padahal Lunlun pintar,” Hari menunjukkan daftar nilai di tabletnya, “nggak superior, tapi lumayan pintar.”
“Pintar tapi nilainya masih kurang cukup untuk standar nilai masuk FK,” aku menebak. Semuanya mengangguk.
Jovan menambahkan, “pokoknya Lunlun harus masuk FK PTN, biar bangga. Dia bilang gitu ke kita, ya kan, Kal?”
Kalina mengiyakan.
Sebagai lembaga bimbingan belajar yang memang bertugas mengantarkan siswa-siswi ke perguruan tinggi terbaik, ini bukan pertama kalinya kami menemukan kasus siswa menjadi korban ambisi orang tua. Sebagian besar siswa yang menyambut baik ambisi itu, dan menjadikan tekanan orang tua sebagai pecut penyemangat yang efektif. Sayangnya, ada sebagian kecil siswa yang malah mengalami reaksi sebaliknya.
Mental siswa patah terkena tekanan itu. Patahannya mencuat ke mana-mana, menjadi kesedihan, kemuraman, dan perlahan, semangatnya melayu. Seperti siswi-siswi yang mengantuk kekenyangan habis makan siang tadi.
Aku mengingat-ingat ekspresi Lunlun di teras minimarket tadi. Dia terlihat bengong, seakan tengah memikirkan banyak hal, namun pada akhirnya tidak ada yang bisa dicerna otaknya. Sosoknya kecil, berdiri di antara galon-galon dan tabung-tabung gas, memegang payung besar di guyuran tengah hujan. Kacamatanya berembun. Jika dijadikan ilustrasi, Lunlun akan jadi gambar bernuansa dingin, kelabu dan depresif.
Aku agak kasihan. Kalau saja kami berkesempatan mengobrol berdua, aku ingin bicara dengan dia. Aku bisa menyemangati siswa, atau minimal, mendengarkan keluh kesah mereka, membuat mereka merasa lebih baik dan bisa bangkit. Rasanya tidak adil melihat ada siswa yang tidak ceria di bimbel ini, di saat semua teman-temannya bisa tertawa-tawa dan bersuara heboh meskipun sama-sama sedang berjuang masuk PTN.
.
Aku baru bisa bertemu dengan Lunlun dua minggu kemudian, saat ada sosialisasi dan pengumuman penting terkait registrasi akun untuk mendaftar perguruan tinggi. Wajahnya terlihat terpaksa. Dia menyeret ransel besar dan berkali-kali menaikkan kacamatanya yang melorot.
“Hai, Lun!” aku menyapa dari ujung meja. Dia mengangguk sopan seperti biasa, lalu cepat-cepat naik ke lantai dua. Di ruanganpun, dia mengambil tempat paling pojok, jauh dari keramaian teman-temannya. Tangannya sibuk bermain gim daring di ponsel.
“Lun, sosialisasi sudah mau mulai, ayo mainnya nanti,” tegur Kalina lembut. Dia segera menyelipkan ponsel ke bawah meja. Matanya kosong tanpa antusiasme.
Layar proyeksi di depan kelas berganti-ganti, menayangkan data statistik tentang pendaftaran PTN, keberhasilan masuk jurusan, dan informasi lain. Semakin banyak informasi yang disampaikan, semakin Lunlun enggan menyimak. Baru sepertiga waktu berlalu, dia sudah membuka ponsel lagi, menyalakan gimnya.
.
Hujan turun deras lagi seusai sosialisasi. Aku mengambil kesempatan untuk mendekati Lunlun yang tengah duduk di teras. “Lun, nunggu hujan? Atau nunggu dijemput?” aku menyapa sambil ikut duduk di bangku tunggu.
“Nunggu hujan reda,” jawabnya.
Aku berusaha membuka obrolan, “Kamu pulang ke mana, Lun?”
“Wilis Asri. Perumahan Permata Mulia,” dia menjawab pelan
“Oh ya? Dekat sama rumahnya Kak Kalina, dong? Kalau sama apotek Wilis Asri itu sebelah mana?” aku mencoba berbasa-basi, memancing Lunlun untuk bicara.
Biasanya siswa-siswa akan terpancing untuk bicara lebih lanjut. Lunlun menjawab, namun kutebak, dia menjawab hanya demi sopan santun. Matanya menunjukkan sorot tanpa bersemangat, dan bahunya selalu cepat-cepat dipalingkan dari arahku.
Aku selalu merasa menjadi guru yang andal dalam bersosialisasi dengan siswa. Banyak siswa yang akrab denganku. Siswa yang paling nakalpun bisa kuajak duduk dan bicara baik-baik. Siswa paling pendiampun bisa kuajak tertawa. Mereka mengakuiku sebagai guru yang asyik. Apalagi aku guru bimbingan belajar. Hubunganku dengan para siswa jauh lebih santai daripada guru-guru SMA biasa
Penolakan Lunlun sedikit menyentak hati. Apakah keasyikanku sudah berkurang? Atau memang karena Lunlun yang terlalu pendiam dan depresif?
“Lun, kamu sudah lama nggak masuk kelas saya,” aku berkata dengan ayunan seceria mungkin, supaya dia tidak merasa ditegur, “kalau butuh pelajaran tambahan, bisa langsung hubungi saya, ya!”
“Iya, Pak,” dia mengangguk sopan, lalu berbalik menghadap hujan lagi.
“Lunlun sudah mengisi daftar rencana kuliah belum?” aku bertanya lagi. Setiap siswa di sini memang wajib mengisi daftar rencana kuliah yang cukup panjang. Aku tahu Lunlun belum mengumpulkannya.
“Belum,” dia jujur.
“Yuk, isi dulu, mumpung ada waktu. Cuma sebentar, kok. Saya temani,” kataku. Lunlun kelihatan keberatan, namun juga sungkan. Aku tidak yakin apakah ini cara yang baik, tapi aku merasa memang harus memaksa Lunlun keluar dari fase mengisolasi diri.
Dengan gontai, dia masuk lagi ke ruang utama, duduk di pojok sambil menaikkan kacamatanya yang melorot. Aku mengambilkan tablet bimbel dan meminta dia mengetik. Aku juga membawakannya minum hangat. “Ini memang dibuat sama Kak Kalina buat siswa-siswa. Enak kan, dingin-dingin minum teh hangat,” aku memberitahu. Minuman hangat di tengah hujan selalu menyamankan suasana
Dia meminum tehnya dengan sopan. Jari-jarinya yang kurus bergerak di layar, mengisi data diri terlebih dahulu. Aku baru sadar bahwa Lunlun sengaja menutupi kolom namanya. Dia malu memiliki nama yang menurut kebanyakan orang aneh. Kudengar dia pernah dirundung gara-gara namanya.
Lunlun terlihat ragu-ragu saat memilih jurusan kuliah yang dia tuju. Aku mengingatkan dengan ceria bahwa Lunlun harus segera memutuskan, karena sebentar lagi, pendaftaran dibuka. Aku juga berusaha mengajaknya bicara, dan bertanya dengan nada canda.
Dia menggulung layar beberapa kali. Jarinya gemetar. Aku agak menyesal mendesaknya. Aku rasa dia malah semakin tertekan. Jadi, aku berpura-pura pergi mengambil minum dan berlama-lama di ruang guru, mengobrol dahulu dengan beberapa pengajar selama sepuluh menit. Aku berniat memberi Lunlun ruang.
Saat aku kembali, Lunlun sudah tidak ada di kursi semula. Tehnya masih sisa banyak. Tablet yang tadi kupinjamkan sudah dia kembalikan ke meja resepsionis, dan dia batal mengisi daftar rencana kuliah. Hujan masih deras, dan kubayangkan dia berlari menembus hujan tanpa perlindungan. Dia lebih rela berbasah-basah daripada membicarakan masa depan.
Rasa bersalah mengempasku keras, seperti hujan deras.
Aku segera mengambil payung dan berniat menyusul Lunlun, berharap menemukan dia di antara tabung gas dan galon di depan minimarket seperti kemarin. Sayangnya, Lunlun tidak ada di mana-mana. Pedagang-pedagang di sekitar trotoar sampai heran melihat pria dewasa berseragam bimbel oranye ini berputar-putar sendiri di pinggir jalan.
Lunlun tidak pernah kelihatan lagi sejak saat itu.
.
Dulu, saat pertama kali aku berkarir sebagai pengajar bimbel, aku dicekoki aneka seminar tentang bagaimana menjadi guru yang baik dan benar. Salah satu mantra terkutuk bagi seorang pengajar adalah, “cara mengajarku sudah bagus.”
Sekarang aku menambahkan satu lagi mantra terlarang ke dalam daftar. “Aku sudah jadi guru yang asyik kok.” Karena tidak semua siswa dapat didekati dengan cara yang asyik seperti gerombolan siswi yang suka bergosip.
Aku mendekati Lunlun dengan tingkat kepercaya dirian yang terlalu tinggi, berekspektasi dia akan tunduk seperti siswa-siswa lainnya, tanpa tahu apa yang melatarbelakangi masalahnya. Pada akhirnya, pendekatanku malah jadi tidak berbeda dari tekanan Mamanya. Mematahkan, bukan menghubungkan. Mengubur, bukan membangkitkan.
Aku mengonsultasikan ini kepada beberapa rekan. Namun pada akhirnya, mereka hanya bisa berkata, “Lunlun kan nggak datang ke sini. Di luar sana, dia bukan tanggung jawab kita. Kalau kelak Lunlun gagal masuk perguruan tinggi, itu bukan salah kita.”
Hatiku remuk. Entah karena memang sepenuhnya berempati, atau karena sakit hati pribadi karena merasa gagal merangkul siswa.
.
Kudengar, Lunlun mengundurkan diri dari bimbel.
“Aku dengar cerita soal Lunlun,” Kalina memberitahuku, “Lunlun sakit. Dia masuk rumah sakit hampir tiga minggu.”
Aku baru ingat rumah Kalina dekat dengan rumah Lunlun. Dia pasti mendengar cerita ini dari tetangga sekitar atau semacamnya.
“Lunlun sakit apa?” aku bertanya.
Kalina mendongak, melihatku dengan pandangan sedih. “Asam lambung parah. Sampai muntah darah. Stres berat katanya.”
Kalina melanjutkan, “Mamanya berambisi Lunlun masuk fakultas kedokteran UGM atau UI. Pokoknya harus banget dua itu. Katanya malu kalau nggak masuk ke sana, karena sepupunya atau siapanya gitu masuknya ke UGM. Setelah dianalisa, nilai Lunlun itu bisa masuk ke FK, tapi di universitas yang mungkin peringkatnya di bawah UGM atau UI, tapi Mamanya nggak mau tahu. Mamanya Lunlun single parent. Tahu nggak sih, tipikal ibu-ibu ambis yang nggak pengen kalah saing sama siapa-siapa. Akhirnya dia menuntut anak supaya bisa membanggakan dia. Nah, Lunlun ini jadi kayak nggak punya pelindung di rumah. Di sekolah juga dia nggak punya banyak teman. Lunlun tertekan.”
Aku mengangguk, mengerti.
Kalina membuka aplikasi internal kantor, dan membuka menu daftar siswa. Aku melihat saat Kalina menekan tombol delete di samping nama Lunlun di layar. Ralunda Kristanoba Roswanda Maldiba lengkapnya. Dia akan kuingat sebagai siswa yang memberiku pelajaran berharga tentang mantra terlarang itu.