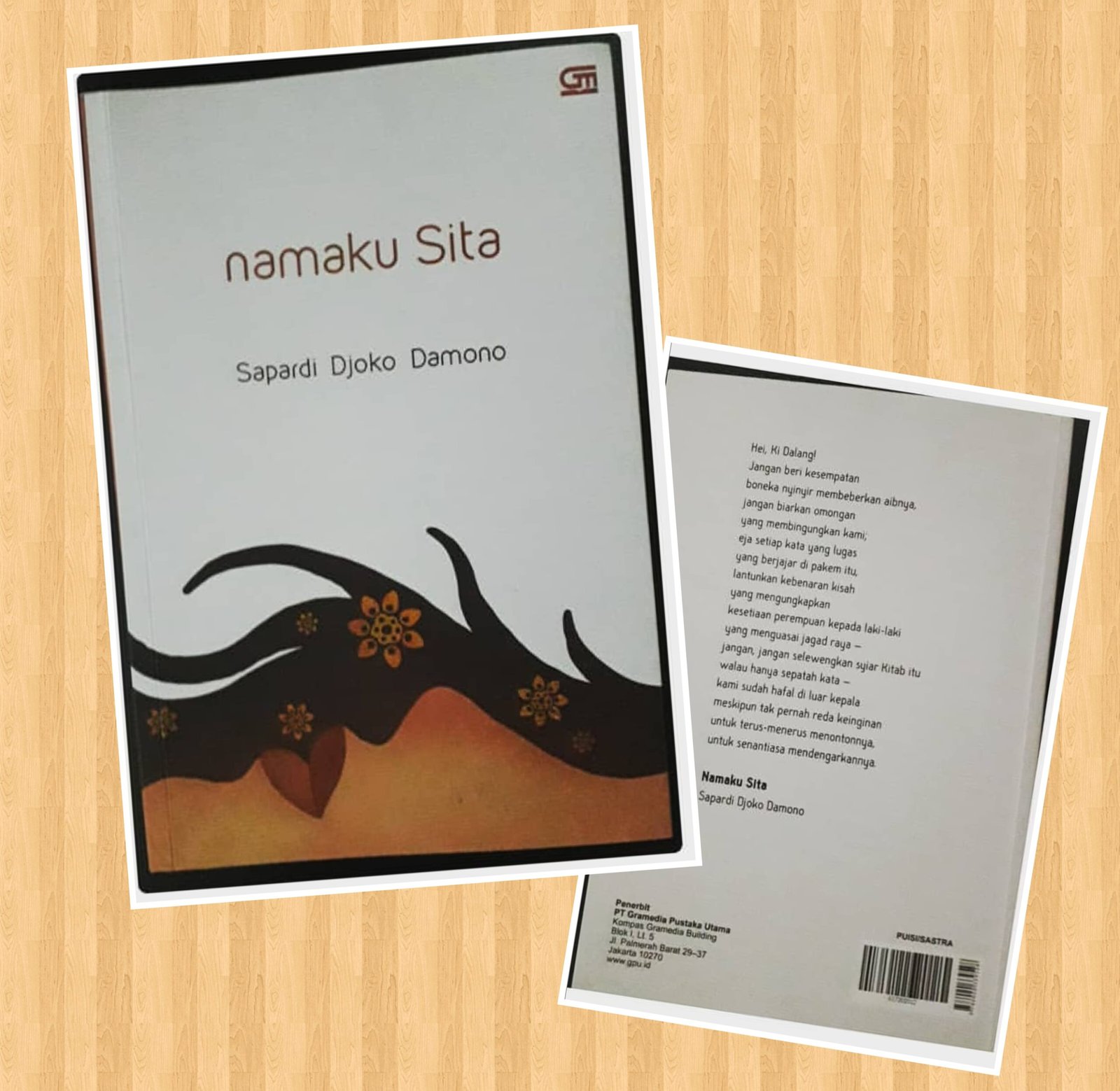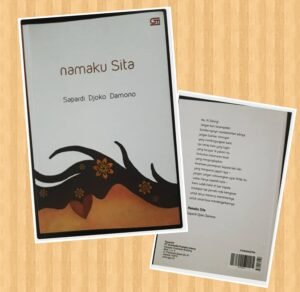Setiap peringatan hari Guru, media sosial dipenuhi ucapan selamat. Panggung dihiasi bunga, dan pidato semangat kembali terdengar. Guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa, pelita dalam gelap, dan ujung tombak peradaban. Namun, setelah mikrofon mati dan bunga layu, hidup guru kembali ke kenyataan yang tidak sejahtera.
Sebagai orang yang telah 22 tahun mengabdikan diri di dunia pendidikan, saya tidak ingin menyalahkan siapa pun. Saya hanya ingin berbicara jujur kepada masyarakat, pengambil kebijakan, dan semua yang peduli pada masa depan bangsa. Kita tidak bisa bicara tentang kualitas pendidikan tanpa membahas kesejahteraan guru. Bagaimana mungkin seseorang mendidik sepenuh hati jika hidupnya penuh kesulitan?
Mari kita mulai dari penghasilan. Hingga kini, banyak guru honorer digaji di bawah standar layak hidup. Di beberapa daerah, ada guru yang menerima kurang dari Rp 500.000 per bulan. Pembayaran pun sering terlambat. Untuk bertahan hidup, mereka jadi tukang ojek, pedagang kecil, atau buruh serabutan. Pekerjaan mulia di pagi hari sering diimbangi dengan kerja keras di malam hari.
Realita ini sangat menyedihkan. Kita berharap guru mendidik dengan semangat, menginspirasi peserta didik, dan mengintegrasikan teknologi. Namun, banyak dari mereka kesulitan membeli paket data untuk platform pembelajaran atau harus meminjam laptop. Ironis, bukan? Guru harus profesional, tetapi hidup mereka tidak layak untuk membangun masa depan.
Namun, kesejahteraan guru bukan hanya soal uang. Ada juga kepastian status kerja, perlindungan hukum, dan pengakuan profesional. Masih banyak guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun, tetapi belum diangkat menjadi ASN atau PPPK. Status mereka menggantung, terombang-ambing oleh regulasi yang berubah-ubah. Setiap tahun, mereka mengikuti tes, bersaing dengan guru yang lebih muda, dan sering gagal karena sistem tidak mendukung pengalaman.
Lebih menyedihkan, ketika guru menghadapi masalah, banyak yang harus menanggung tekanan sosial dan hukum sendiri. Banyak kasus di mana guru dilaporkan oleh orang tua peserta didik hanya karena dianggap tegas. Daripada mendapat perlindungan, mereka malah menjadi tersangka hanya karena menjalankan tugas. Saat itu, institusi pendidikan jarang hadir untuk membela. Guru menjadi pihak paling lemah dalam sistem pendidikan. Mudah disalahkan, tetapi jarang dibela.
Bagaimana dengan aspek psikologis? Ini sering luput dari perhatian. Guru dituntut terus belajar, mengikuti pelatihan, menyusun modul, memenuhi administrasi, dan mengajar dengan metode kreatif. Tapi berapa banyak dari mereka yang mendapat waktu untuk istirahat atau didengarkan keluhannya?
Saya pernah berbincang dengan guru senior yang berkata, “Yang bikin lelah itu bukan peserta didik, tapi sistem.” Kalimat ini sangat membekas. Beban administrasi dan tekanan birokrasi sering lebih berat daripada mendidik peserta didik. Guru bisa sabar menghadapi anak bandel, tetapi frustrasi saat berhadapan dengan tumpukan laporan yang seharusnya ditangani dinas luar pendidikan. Alih-alih menciptakan ruang kreatif, guru justru terjebak dalam dokumen yang bisa disederhanakan.
Fenomena kelelahan mental atau burnout di kalangan guru nyata dan tidak bisa diabaikan. Jika dibiarkan, ini akan menggerogoti semangat mengajar. Guru yang mentalnya lelah tidak akan mampu memberikan pembelajaran yang bermakna. Jika ini terjadi secara massal, kita sedang menghadapi krisis diam dalam pendidikan.
Apakah kita benar-benar ingin memperbaiki kualitas pendidikan? Jika ya, langkah pertama adalah memperhatikan kesejahteraan guru. Ini bukan hanya soal program insentif, tetapi reformasi sistemik yang menyentuh akar masalah. Gaji yang layak dan tepat waktu penting. Begitu juga dengan kepastian status kerja. Perlindungan hukum yang jelas dan pengembangan profesi sesuai kebutuhan juga harus ada.
Kita bisa belajar dari negara yang menghormati guru sebagai profesi prestisius. Di Finlandia, menjadi guru adalah impian banyak pemuda. Gajinya layak, guru dihormati, dan diberi kepercayaan dalam mendesain pembelajaran. Pendidikan mereka berkualitas. Ini karena pendidik mereka bekerja sepenuh hati, bukan karena lelah.
Indonesia bisa saja memiliki kurikulum yang bagus, teknologi canggih, atau gedung megah. Namun, semua itu tidak akan berarti jika guru tidak diberdayakan dengan baik. Pendidikan adalah soal hubungan manusia, bukan sekadar sistem. Hubungan ini akan baik jika guru merasa dihargai dan didukung.
Penghargaan terhadap guru bukan hadiah, tetapi hak. Guru bukan pekerja rendahan yang berjuang sendiri, tetapi pilar utama masa depan bangsa. Jika negara ingin mencerdaskan bangsa, perhatian kepada guru harus menjadi prioritas.
Sebagai guru, saya tidak minta disanjung. Saya hanya ingin dihargai secara manusiawi. Agar saya dan rekan-rekan bisa mengajar dengan tenang, bukan dengan kekhawatiran. Kami ingin membimbing peserta didik ke masa depan yang cerah, tidak lewat jalan yang gelap.
Kesejahteraan guru bukan semata angka di rekening, tetapi rasa aman, penghargaan, dan kepastian atas profesi yang mereka tekuni. Ini adalah investasi jangka panjang bangsa. Jika kita terus menutup mata, bukan hanya guru yang kehilangan harapan, tetapi generasi mendatang yang akan menanggung akibatnya. Mari berhenti memuja guru hanya di atas panggung seremonial. Saatnya menjadikan mereka subjek kebijakan, bukan sekadar objek pujian. Sebab, bangsa yang besar bukan hanya menghormati pahlawannya saat upacara, tetapi menjamin mereka hidup layak setiap hari.
Kepada yang berwenang dan peduli, tolong jangan biarkan kesejahteraan guru hanya jadi wacana musiman. Jangan jadikan kami sekadar simbol perjuangan. Jadikan kami bagian dari perubahan nyata. Setiap anak hebat memiliki guru yang berjuang. Mereka berjuang dalam diam, lelah, dan penuh harapan.